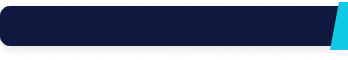Aksi Koboi Duterte Berantas Narkoba Terinspirasi Operasi Petrus Soeharto?
loading...

Presiden Filipina Rodrigo Duterte
A
A
A
JAKARTA - Aksi koboi Rodrigo Duterte dalam memerangi narkoba tak hanya menyikut demokrasi tapi juga mulai mengangkangi kebebasan pers. Dua jurnalis senior Filipina yang gencar mengkritisi aksi main tembak sang Presiden terhadap bandar maupun sekadar pemakai narkoba, Senin (15/6) lalu, merasakan sikap tangan besi itu. Maria Ressa dan Reynaldo Santos dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Manila Regional Trial Court (RTC) Branch 46.
Hakim Rainelda Estacio-Montesa memerintahkan keduanya membayar 200.000 peso Filipina (Rp 56 juta) untuk kerusakan moral dan 200.000 peso lainnya untuk peringatan. Ressa dan Santos yang dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik juga terancam menjalani hukuman minimal enam tahun dan maksimal tujuh tahun.
Ressa dan Santos tidak perlu masuk penjara setelah membayar uang jaminan seraya mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA).
Kedua jurnalis diajukan ke meja hijau atas laporan pengusaha Wilfredo Keng yang merasa nama baiknya dicemari. Dikutip dari Inquirer.net, kasus berawal dari sebuah artikel tahun 2012 yang ditulis oleh Santos yang mengklaim bahwa Keng meminjamkan kendaraan sport miliknya kepada Ketua MA Renato Corona.
Artikel yang sama juga mengutip laporan intelijen yang mengatakan bahwa Keng telah diawasi oleh Dewan Keamanan Nasional karena diduga terlibat dalam perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba.
Keng mengajukan pengaduan pencemaran nama baik dunia maya pada 2017 atau lima tahun setelah artikel itu pertama kali ditayangkan dan tiga tahun setelah itu ditayangkan kembali karena kesalahan ketik.
Meski berita itu tidak langsung mengkritisi Duterte, para pendukung kebebasan pers berpendapat, wartawan senior itu menjadi sasaran Presiden Rodrigo Duterte, karena sejumlah laporan kritis Rappler terkait pemerintah. Apalagi Ressa telah berulang kaki ditangkap akibat kritik tajamnya ke Duterte. Menurut Rappler, ini kasus ketujuh yang membelit Ressa dan kasus ke-11 yang melibatkan Rappler.
Kritik tajam yang kerap dilontarkan Ressa melalui situs Rappler memang membuat Duterte geram. Presiden berusia 74 tahun dan para pendukungnya lantas menuding berita negatif tentang kebijakannya sebagai hoax.
Eksistensi situs Rappler, berdiri tahun 2012, juga kena bidik Duterte. Situs yang didirikan oleh wanita kelahiran Filipina dan berpaspor Amerika Serikat (AS) itu dituduh menghindari kewajiban membayar pajak serta melanggar undang-undang yang melarang kepemilikan asing atas media lokal.
Ressa, 56 tahun, lulusan Princeton University, pernah bekerja sebagai kepala biro jaringan CNN untuk Filipina dan Indonesia –ia berdinas di Indonesia pada masa demo anti Orde Baru meruyak hingga Presiden Soeharto meletakkan jabatan-- serta menjabat kepala divisi pemberitaan di kanal televisi negerinya, ABS-CBN.
Rappler mulai popular tahun 2015, saat walikota Davao yang waktu itu dijabat oleh Duterte berkata kepada Ressa bahwa dia telah membunuh tiga orang. Ressa memang banyak meliput tentang perang narkoba yang dilancarkan oleh Duterte dan telah merenggut ribuan nyawa warga Filipina.
Hingga kini, Rappler termasuk satu dari segelintir media di Filipina yang bersikap sangat kritis terhadap kebijakan Presiden Duterte. Rappler lantas dilarang meliput kegiatan resmi Presiden dan izin operasionalnya terancam dicabut.
Tentu saja vonis bersalah bagi Ressa dan Santos mendapat perhatian dunia internasional. “Pemerintah AS merasa prihatin oleh putusan pengadilan terhadap jurnalis Maria Ressa dan Reynaldo Santos, dan meminta resolusi kasus ini dengan cara memperkuat komitmen AS dan Filipina terhadap kebebasan berekspresi termasuk bagi insan pers,” kata Morgan Ortus, juru bicara deplu AS, dalam pernyataan pada Selasa (17/6) lalu.
Duterte memang dikenal gemar bersikap keras terhadap lawan politik. Dia juga melakukan kampanye perang melawan narkoba, yang membuat ribuan orang tewas. Human Right Watch memperkirakan sejak Duterte diambil sumpahnya sebagai Presiden tahun 2016 sudah lebih dari 12.000 orang mati ditembak akibat dicurigai memperjualbelikan narkoba. Sebuah pekiraan lain bahkan menyampaikan angka yang lebih tinggi, 27.000 jiwa!.
Nyali Duterte tampaknya tak ciut sedikit pun dengan Dewan HAM PBB yang Juli tahun lalu menerbitkan Resolusi mengenai perlindungan HAM di Filipina. Resolusi itu lantas diikuti oleh ICC (Pengadilan Kriminal Internasional) yang sejak 2018 melakukan investigasi untuk merampungkan laporannya pada tahun ini.
Ia bahkan menantang ICC untuk memenjarakan atau menggantungnya.Ia pun bilang tak sudi bekerja sama dengan pihak asing jika diadili dalam kasus ini. “Anda tidak bisa menakuti saya dengan penjara di ICC. Saya tidak akan pernah menjawab orang-orang kulit putih ini,” kata Duterte seperti dilansir Channel News Asia pada 20 Desember 2019.
“Saya tidak akan pernah menjawab pertanyaan dari Anda. Bagi saya itu omong kosong. Saya hanya bertanggung jawab kepada bangsa Filipina. Orang Filipina yang akan menilai,” katanya seperti dilansir Inquirer.
Duterte secara sepihak membatalkan keanggotaan negaranya di ICC meski tanpa persetujuan parlemen Filipina. Dia beralasan ICC telah mengabaikan prinsip praduga tidak bersalah. Namun, lembaga advokasi Amnesty International menyebut tindakan Duterte sebagai pengecut dan keliru.
Jaksa ICC mengatakan yurisdiksi pengadilan ini berlaku terhadap negara yang berstatus anggota saat tindakan kriminal itu terjadi.
Kelompok HAM mengritik perang narkoba Duterte telah menjadi operasi eksekusi sistematis dan upaya menutup-nutupi kejahatan.Polisi menolak tudingan itu dan mengatakan sekitar 7 ribu orang yang tewas merupakan tersangka pengedar narkoba bersenjata yang menolak ditangkap.
Investigasi ICC ini dimulai dari laporan pengacara Jude Sabio pada April 2017. Dia menuding pemerintahan Duterte melakukan kejahatan kemanusiaan karena melakukan pembunuhan ekstra-yudisial berkedok perang narkoba kontroversial.
Korban yang diincar para eksekutor tak hanya bandar yang memang nyata-nyata terlibat dalam bisnis narkoba. Sang presiden juga telah merilis daftar yang lebih panjang pada 2016. Dalam daftar itu ada lebih dari 150 hakim, wali kota, dan pejabat lokal lainnya yang diduga memiliki keterlibatan dengan narkoba.
SINDOnews mencatat ada lima walikota yang ditembak di kantornya. Pertama, David Navarro, wali kota Cebu, yang tewas setelah disergap kelompok bersenjata di dalam tahanan. Selanjutnya, Wali Kota Rolando Espinosa dan Reynaldo Parojinog. Espinosa dieksekusi di ruang tahanan polisi. Adapun Wali Kota Antonio Halili dihabisi saat memimpin upacara di kantornya, Balai Kota Tanauan. Terakhir, Wali Kota Ronda, Mariano Blanco, diberondong pria bersenjata tak dikenal di kantornya. Sadis.
Gencar mengkritisi Duterte, Senator Leila De Lima juga harus menghadapi kenyataan pahit. Ia harus meringkuk di penjara. Kesalahannya adalah mengutuk aksi koboi Futerte dalam memberantas narkoba sejak menjadi wali kota hingga presiden.
De Lima, mantan Menteri Kehakiman, meluncurkan investigasi atas dugaan keterlibatan Duterte dalam pembunuhan di luar proses hukum, telah ditahan selama lebih dari dua tahun atas tuduhan narkoba yang telah dibantahnya. Ia memimpin investigasi pembunuhan massal Duterte pada awal 2017.
Sampai kapan Duterte akan melancarkan aksi koboi? Entahlah. Yang pasti, sesuai konstitusi ia akan berkuasa hingga tahun 2022. Lain cerita jika Dewan HAM PBB menerbitkan Resolusi yang menyatakan Duterte bersalah dalam beberapa hari ke depan.
Soeharto: “Biar Saya Pertanggungjawabkan Terhadap Tuhan”
Jauh sebelum aksi sableng Duterte, di negeri kita juga pernah terjadi aksi serupa tapi tak sama. Jika Duterte melancarkan aksinya terhadap mereka yang terlibat narkoba, Presiden Soeharto (berkuasa dari 1966-1998) melancarkan operasi “Petrus” alias penembakan misterius terhadap pelaku kriminal yang dinilai sangat meresahkan masyarakat.
Ada yang memperkirakan korbannya mencapai 10.000 orang. Tapi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menaksir jumlah korbannnya “hanya” 781 orang.
Seperti Duterte, Soeharto mengakui terus terang operasi itu memang dilakukan atas perintahnya. Dalam otobiografinya, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Presiden RI kedua itu beralasan bahwa petrus sebagai usaha mencegah kejahatan seefektif mungkin dengan harapan menimbulkan efek jera.
“Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan yang tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor! dor! begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan, maka mereka ditembak,” katanya.
“Lalu mayatnya ditinggalkan begitu saja,” lanjutnya. “Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya.”
Berdasarkan pemberitaan media massa yang terbit pada saat itu, sejak awal Januari 1983 Kodam Jaya telah memulai operasi pemberantasan kejahatan dengan nama “Operasi Celurit”. Dalam operasi itu, Kodam Jaya berada langsung di bawah komando Pangkopkamtib Sudomo.
Menurut keterangan Soedomo pada sebuah media cetak di Jakarta, Juli 1983, operasi itu tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menginventarisasi nama-nama pelakunya.
Berita-berita mengenai korban petrus yang marak di media massa menimbulkan silang pendapat. Kepala Bakin (kini BIN/Badan Intelijen Negara) Yoga Soegama menyatakan tak perlu mempersoalkan para penjahat yang mati secara misterius.
Dalam kenyataannya, sebagaimana diberitakan media massa, bertato saja sudah cukup bagi mereka dianggap sebagai penjahat untuk dihabisi oleh petrus. Di berbagai kota mayat-mayat tertembak peluru di dada atau kepala dalam keadaan tangan terikat atau dimasukan ke dalam karung, digeletakkan begitu saja di emperan toko, bantaran kali, dan di semak-semak.
Persoalan petrus yang semula dilakukan secara rahasia lambat laun tersebar di masyarakat dan bahkan mendapatkan perhatian dari dunia luar. Sejumlah organisasi, antara lain Amnesti Internasional, menyoal pembunuhan yang sadistis itu. Namun surat Amnesti Internasional dianggap sepi oleh pemerintah.
LB Moerdani, Panglima ABRI (1983-1988) yang disebut-sebut sebagai salah satu desainer Operasi Petrus itu mengatakan kalau peristiwa itu dipicu oleh perang antargenk. Ia bilang, pembunuhan-pembunuhan itu tak melibatkan tangan ABRI.
Operasi Petrus mendapat kritik tajam dari mantan Wapres Adam Malik. “Jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak, bila perlu diadili hari ini langsung besoknya dieksekusi mati. Jadi syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi,” ujarnya seraya mengingatkan, “Setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran. ”
Pendapat Adam Malik mendapat dukungan dari tokoh pendiri YLBHI Adnan Buyung Nasution. Ia menyatakan jika usaha pemberantasan kejahatan dilakukan hanya dengan main tembak tanpa melalui proses pengadilan maka hal itu tidak menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Padahal kedua masalah tersebut, paparnya, merupakan tuntutan hakiki yang diperjuangkan orang sejak zaman Romawi Kuno. “Jika cara-cara seperti itu terus dilakukan maka lebih baik lembaga pengadilan dibubarkan saja. Jika ada pejabat apapun pangkatnya dan kedudukannya, mengatakan tindakan main dor-doran itu benar, saya tetap mengatakan hal itu adalah salah,” kecamnya.
Soeharto menjawab bahwa alasan petrus karena rakyat kecil telah dipersulit oleh sekelompok manusia jahat di beberapa daerah; mereka dirampok, diperkosa, dan lain-lain. Sementara polisi dan aparat keamanan lainnya boleh dikatakan tidak berdaya, sehingga suatu shock treatment perlu diambil untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi kejahatan.
“Ya, nanti biar saya yang bertanggung jawab kepada Tuhan,” tegasnya.
Setelah saling-silang pendapat di masyarakat dan tekanan dunia internasional, akhirnya pemerintah Orde Baru menghentikan sama sekali operasi tersebut pada 1985.
Kendati begitu, Operasi Petrus masuk dalam daftar 12 pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum terselesaikan oleh pemerintah. Yang lainnya meliputi: peristiwa 1965-1966; peristiwa Talangsari, Lampung 1989; tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II pada 1998-1999; dan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Selanjutnya, penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998; peristiwa Wamena dan Wasior 2001-2003; peristiwa Aceh-Jambo Keupok 2003; peristiwa Aceh-Simpang KKA 1998; peristiwa Aceh Rumoh Geudong 1989; serta peristiwa dukun santet di Jawa Timur 1998-1999.
Lihat Juga: Nasib Gembong Narkoba Mary Jane: Nyaris Dieksekusi di Era Jokowi, Dilepaskan di Era Prabowo
Hakim Rainelda Estacio-Montesa memerintahkan keduanya membayar 200.000 peso Filipina (Rp 56 juta) untuk kerusakan moral dan 200.000 peso lainnya untuk peringatan. Ressa dan Santos yang dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik juga terancam menjalani hukuman minimal enam tahun dan maksimal tujuh tahun.
Ressa dan Santos tidak perlu masuk penjara setelah membayar uang jaminan seraya mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA).
Kedua jurnalis diajukan ke meja hijau atas laporan pengusaha Wilfredo Keng yang merasa nama baiknya dicemari. Dikutip dari Inquirer.net, kasus berawal dari sebuah artikel tahun 2012 yang ditulis oleh Santos yang mengklaim bahwa Keng meminjamkan kendaraan sport miliknya kepada Ketua MA Renato Corona.
Artikel yang sama juga mengutip laporan intelijen yang mengatakan bahwa Keng telah diawasi oleh Dewan Keamanan Nasional karena diduga terlibat dalam perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba.
Keng mengajukan pengaduan pencemaran nama baik dunia maya pada 2017 atau lima tahun setelah artikel itu pertama kali ditayangkan dan tiga tahun setelah itu ditayangkan kembali karena kesalahan ketik.
Meski berita itu tidak langsung mengkritisi Duterte, para pendukung kebebasan pers berpendapat, wartawan senior itu menjadi sasaran Presiden Rodrigo Duterte, karena sejumlah laporan kritis Rappler terkait pemerintah. Apalagi Ressa telah berulang kaki ditangkap akibat kritik tajamnya ke Duterte. Menurut Rappler, ini kasus ketujuh yang membelit Ressa dan kasus ke-11 yang melibatkan Rappler.
Kritik tajam yang kerap dilontarkan Ressa melalui situs Rappler memang membuat Duterte geram. Presiden berusia 74 tahun dan para pendukungnya lantas menuding berita negatif tentang kebijakannya sebagai hoax.
Eksistensi situs Rappler, berdiri tahun 2012, juga kena bidik Duterte. Situs yang didirikan oleh wanita kelahiran Filipina dan berpaspor Amerika Serikat (AS) itu dituduh menghindari kewajiban membayar pajak serta melanggar undang-undang yang melarang kepemilikan asing atas media lokal.
Ressa, 56 tahun, lulusan Princeton University, pernah bekerja sebagai kepala biro jaringan CNN untuk Filipina dan Indonesia –ia berdinas di Indonesia pada masa demo anti Orde Baru meruyak hingga Presiden Soeharto meletakkan jabatan-- serta menjabat kepala divisi pemberitaan di kanal televisi negerinya, ABS-CBN.
Rappler mulai popular tahun 2015, saat walikota Davao yang waktu itu dijabat oleh Duterte berkata kepada Ressa bahwa dia telah membunuh tiga orang. Ressa memang banyak meliput tentang perang narkoba yang dilancarkan oleh Duterte dan telah merenggut ribuan nyawa warga Filipina.
Hingga kini, Rappler termasuk satu dari segelintir media di Filipina yang bersikap sangat kritis terhadap kebijakan Presiden Duterte. Rappler lantas dilarang meliput kegiatan resmi Presiden dan izin operasionalnya terancam dicabut.
Tentu saja vonis bersalah bagi Ressa dan Santos mendapat perhatian dunia internasional. “Pemerintah AS merasa prihatin oleh putusan pengadilan terhadap jurnalis Maria Ressa dan Reynaldo Santos, dan meminta resolusi kasus ini dengan cara memperkuat komitmen AS dan Filipina terhadap kebebasan berekspresi termasuk bagi insan pers,” kata Morgan Ortus, juru bicara deplu AS, dalam pernyataan pada Selasa (17/6) lalu.
Duterte memang dikenal gemar bersikap keras terhadap lawan politik. Dia juga melakukan kampanye perang melawan narkoba, yang membuat ribuan orang tewas. Human Right Watch memperkirakan sejak Duterte diambil sumpahnya sebagai Presiden tahun 2016 sudah lebih dari 12.000 orang mati ditembak akibat dicurigai memperjualbelikan narkoba. Sebuah pekiraan lain bahkan menyampaikan angka yang lebih tinggi, 27.000 jiwa!.
Nyali Duterte tampaknya tak ciut sedikit pun dengan Dewan HAM PBB yang Juli tahun lalu menerbitkan Resolusi mengenai perlindungan HAM di Filipina. Resolusi itu lantas diikuti oleh ICC (Pengadilan Kriminal Internasional) yang sejak 2018 melakukan investigasi untuk merampungkan laporannya pada tahun ini.
Ia bahkan menantang ICC untuk memenjarakan atau menggantungnya.Ia pun bilang tak sudi bekerja sama dengan pihak asing jika diadili dalam kasus ini. “Anda tidak bisa menakuti saya dengan penjara di ICC. Saya tidak akan pernah menjawab orang-orang kulit putih ini,” kata Duterte seperti dilansir Channel News Asia pada 20 Desember 2019.
“Saya tidak akan pernah menjawab pertanyaan dari Anda. Bagi saya itu omong kosong. Saya hanya bertanggung jawab kepada bangsa Filipina. Orang Filipina yang akan menilai,” katanya seperti dilansir Inquirer.
Duterte secara sepihak membatalkan keanggotaan negaranya di ICC meski tanpa persetujuan parlemen Filipina. Dia beralasan ICC telah mengabaikan prinsip praduga tidak bersalah. Namun, lembaga advokasi Amnesty International menyebut tindakan Duterte sebagai pengecut dan keliru.
Jaksa ICC mengatakan yurisdiksi pengadilan ini berlaku terhadap negara yang berstatus anggota saat tindakan kriminal itu terjadi.
Kelompok HAM mengritik perang narkoba Duterte telah menjadi operasi eksekusi sistematis dan upaya menutup-nutupi kejahatan.Polisi menolak tudingan itu dan mengatakan sekitar 7 ribu orang yang tewas merupakan tersangka pengedar narkoba bersenjata yang menolak ditangkap.
Investigasi ICC ini dimulai dari laporan pengacara Jude Sabio pada April 2017. Dia menuding pemerintahan Duterte melakukan kejahatan kemanusiaan karena melakukan pembunuhan ekstra-yudisial berkedok perang narkoba kontroversial.
Korban yang diincar para eksekutor tak hanya bandar yang memang nyata-nyata terlibat dalam bisnis narkoba. Sang presiden juga telah merilis daftar yang lebih panjang pada 2016. Dalam daftar itu ada lebih dari 150 hakim, wali kota, dan pejabat lokal lainnya yang diduga memiliki keterlibatan dengan narkoba.
SINDOnews mencatat ada lima walikota yang ditembak di kantornya. Pertama, David Navarro, wali kota Cebu, yang tewas setelah disergap kelompok bersenjata di dalam tahanan. Selanjutnya, Wali Kota Rolando Espinosa dan Reynaldo Parojinog. Espinosa dieksekusi di ruang tahanan polisi. Adapun Wali Kota Antonio Halili dihabisi saat memimpin upacara di kantornya, Balai Kota Tanauan. Terakhir, Wali Kota Ronda, Mariano Blanco, diberondong pria bersenjata tak dikenal di kantornya. Sadis.
Gencar mengkritisi Duterte, Senator Leila De Lima juga harus menghadapi kenyataan pahit. Ia harus meringkuk di penjara. Kesalahannya adalah mengutuk aksi koboi Futerte dalam memberantas narkoba sejak menjadi wali kota hingga presiden.
De Lima, mantan Menteri Kehakiman, meluncurkan investigasi atas dugaan keterlibatan Duterte dalam pembunuhan di luar proses hukum, telah ditahan selama lebih dari dua tahun atas tuduhan narkoba yang telah dibantahnya. Ia memimpin investigasi pembunuhan massal Duterte pada awal 2017.
Sampai kapan Duterte akan melancarkan aksi koboi? Entahlah. Yang pasti, sesuai konstitusi ia akan berkuasa hingga tahun 2022. Lain cerita jika Dewan HAM PBB menerbitkan Resolusi yang menyatakan Duterte bersalah dalam beberapa hari ke depan.
Soeharto: “Biar Saya Pertanggungjawabkan Terhadap Tuhan”
Jauh sebelum aksi sableng Duterte, di negeri kita juga pernah terjadi aksi serupa tapi tak sama. Jika Duterte melancarkan aksinya terhadap mereka yang terlibat narkoba, Presiden Soeharto (berkuasa dari 1966-1998) melancarkan operasi “Petrus” alias penembakan misterius terhadap pelaku kriminal yang dinilai sangat meresahkan masyarakat.
Ada yang memperkirakan korbannya mencapai 10.000 orang. Tapi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menaksir jumlah korbannnya “hanya” 781 orang.
Seperti Duterte, Soeharto mengakui terus terang operasi itu memang dilakukan atas perintahnya. Dalam otobiografinya, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Presiden RI kedua itu beralasan bahwa petrus sebagai usaha mencegah kejahatan seefektif mungkin dengan harapan menimbulkan efek jera.
“Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan yang tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor! dor! begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan, maka mereka ditembak,” katanya.
“Lalu mayatnya ditinggalkan begitu saja,” lanjutnya. “Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya.”
Berdasarkan pemberitaan media massa yang terbit pada saat itu, sejak awal Januari 1983 Kodam Jaya telah memulai operasi pemberantasan kejahatan dengan nama “Operasi Celurit”. Dalam operasi itu, Kodam Jaya berada langsung di bawah komando Pangkopkamtib Sudomo.
Menurut keterangan Soedomo pada sebuah media cetak di Jakarta, Juli 1983, operasi itu tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menginventarisasi nama-nama pelakunya.
Berita-berita mengenai korban petrus yang marak di media massa menimbulkan silang pendapat. Kepala Bakin (kini BIN/Badan Intelijen Negara) Yoga Soegama menyatakan tak perlu mempersoalkan para penjahat yang mati secara misterius.
Dalam kenyataannya, sebagaimana diberitakan media massa, bertato saja sudah cukup bagi mereka dianggap sebagai penjahat untuk dihabisi oleh petrus. Di berbagai kota mayat-mayat tertembak peluru di dada atau kepala dalam keadaan tangan terikat atau dimasukan ke dalam karung, digeletakkan begitu saja di emperan toko, bantaran kali, dan di semak-semak.
Persoalan petrus yang semula dilakukan secara rahasia lambat laun tersebar di masyarakat dan bahkan mendapatkan perhatian dari dunia luar. Sejumlah organisasi, antara lain Amnesti Internasional, menyoal pembunuhan yang sadistis itu. Namun surat Amnesti Internasional dianggap sepi oleh pemerintah.
LB Moerdani, Panglima ABRI (1983-1988) yang disebut-sebut sebagai salah satu desainer Operasi Petrus itu mengatakan kalau peristiwa itu dipicu oleh perang antargenk. Ia bilang, pembunuhan-pembunuhan itu tak melibatkan tangan ABRI.
Operasi Petrus mendapat kritik tajam dari mantan Wapres Adam Malik. “Jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak, bila perlu diadili hari ini langsung besoknya dieksekusi mati. Jadi syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi,” ujarnya seraya mengingatkan, “Setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran. ”
Pendapat Adam Malik mendapat dukungan dari tokoh pendiri YLBHI Adnan Buyung Nasution. Ia menyatakan jika usaha pemberantasan kejahatan dilakukan hanya dengan main tembak tanpa melalui proses pengadilan maka hal itu tidak menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Padahal kedua masalah tersebut, paparnya, merupakan tuntutan hakiki yang diperjuangkan orang sejak zaman Romawi Kuno. “Jika cara-cara seperti itu terus dilakukan maka lebih baik lembaga pengadilan dibubarkan saja. Jika ada pejabat apapun pangkatnya dan kedudukannya, mengatakan tindakan main dor-doran itu benar, saya tetap mengatakan hal itu adalah salah,” kecamnya.
Soeharto menjawab bahwa alasan petrus karena rakyat kecil telah dipersulit oleh sekelompok manusia jahat di beberapa daerah; mereka dirampok, diperkosa, dan lain-lain. Sementara polisi dan aparat keamanan lainnya boleh dikatakan tidak berdaya, sehingga suatu shock treatment perlu diambil untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi kejahatan.
“Ya, nanti biar saya yang bertanggung jawab kepada Tuhan,” tegasnya.
Setelah saling-silang pendapat di masyarakat dan tekanan dunia internasional, akhirnya pemerintah Orde Baru menghentikan sama sekali operasi tersebut pada 1985.
Kendati begitu, Operasi Petrus masuk dalam daftar 12 pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum terselesaikan oleh pemerintah. Yang lainnya meliputi: peristiwa 1965-1966; peristiwa Talangsari, Lampung 1989; tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II pada 1998-1999; dan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Selanjutnya, penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998; peristiwa Wamena dan Wasior 2001-2003; peristiwa Aceh-Jambo Keupok 2003; peristiwa Aceh-Simpang KKA 1998; peristiwa Aceh Rumoh Geudong 1989; serta peristiwa dukun santet di Jawa Timur 1998-1999.
Lihat Juga: Nasib Gembong Narkoba Mary Jane: Nyaris Dieksekusi di Era Jokowi, Dilepaskan di Era Prabowo
(rza)