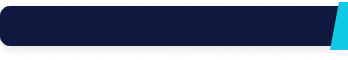Ibu-ibu Palestina di Gaza Ini Melahirkan Anak pada 7 Oktober, Bayi Mereka Hanya Mengenal Perang
loading...

Ibu-ibu Palestina yang melahirkan anaknya pada 7 Oktober mengalami banyak penderitaan. Foto/AP
A
A
A
GAZA - Roket melesat menembus langit pagi di Gaza pada 7 Oktober ketika Amal Al-Taweel bergegas ke rumah sakit di dekat kamp pengungsi Nuseirat, dalam kondisi sudah melahirkan. Setelah kelahiran yang sulit, dia dan suaminya, Mustafa, akhirnya bisa menggendong Ali, anak yang mereka usahakan selama tiga tahun.
Air ketuban Rola Saqer pecah hari itu ketika dia berlindung dari serangan udara Israel di Beit Lahia, sebuah kota Gaza dekat tempat militan Hamas melintasi perbatasan beberapa jam sebelumnya dalam serangan yang mengawali perang. Dia dan suaminya, Mohammed Zaqout, telah berusaha untuk memiliki anak selama lima tahun, dan bahkan ledakan mengerikan di sekitarnya tidak menghentikan mereka untuk pergi ke rumah sakit untuk melahirkan bayi mereka malam itu. Saqer melahirkan Masa, nama yang berarti berlian dalam bahasa Arab.
Keluarga-keluarga muncul dari rumah sakit menuju dunia yang berubah. Pada hari kedua kehidupan bayi-bayi tersebut, Israel menyatakan perang terhadap Hamas dan jet tempurnya menyerbu lingkungan tempat Ali dan Masa seharusnya dibesarkan. Dalam enam bulan sejak anak-anak mereka lahir, pasangan tersebut telah mengalami cobaan sebagai orang tua dini dengan latar belakang konflik brutal.
Rumah-rumah keluarga tersebut rata dengan serangan udara, dan mereka tidak memiliki tempat berlindung yang dapat diandalkan serta sedikit akses terhadap perawatan medis dan perlengkapan bayi. Bayi-bayi tersebut kelaparan, dan terlepas dari semua rencana yang dibuat oleh pasangan tersebut sebelum perang, mereka khawatir nyawa yang mereka harapkan untuk diberikan kepada anak-anak mereka akan hilang.
“Saya sedang mempersiapkannya untuk kehidupan lain, kehidupan yang indah, namun perang mengubah semua hal ini,” kata Amal Al-Taweel kepada The Associated Press. “Kami hampir tidak menjalani hidup hari demi hari, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada perencanaan.”
Saqer mengingat kembali harapannya sebelum perang.
“Ini putriku satu-satunya,” katanya sambil mengayunkan Masa dengan lembut dalam buaiannya. “Saya menyiapkan banyak barang dan pakaian untuknya. Saya membelikannya lemari seminggu sebelum perang. Saya juga merencanakan ulang tahunnya dan segalanya. Perang datang dan menghancurkan segalanya.”
Keluarga Al-Taweel menghabiskan hari-hari pertama kehidupan Ali berpindah-pindah rumah dan rumah kerabatnya untuk mencari keselamatan. Gedung-gedung di dekatnya terus dihantam – pertama di sebelah rumah saudara perempuan Amal, dan kemudian di sebelah rumah orang tuanya.
Ketika keluarga tersebut berlindung di rumah pada tanggal 20 Oktober, pihak berwenang Israel mengeluarkan perintah evakuasi yang memperingatkan bahwa serangan akan segera terjadi dan penduduk memiliki waktu 10 menit untuk pergi.
“Saya harus mengungsi. Saya tidak dapat menerima apa pun; tidak ada tanda pengenal, tidak ada ijazah universitas, tidak ada pakaian untuk anak saya – tidak ada apa-apa,” kata Amal Al-Taweel. “Bahkan susu, popok, dan mainan yang saya belikan untuk anak saya.”
Keluarga tersebut mencari perlindungan sementara di rumah orang tua Amal di Gaza tengah, di mana 15 anggota keluarga mengungsi.
Tak jauh dari situ, Saqer, suami dan putrinya berdesakan di rumah seorang kerabat dengan dua kamar tidur yang dihuni lebih dari 80 anggota keluarga besarnya. Saking ramainya, katanya, kerabat laki-lakinya membangun tenda di luar agar perempuan dan anak-anak bisa tidur lebih nyaman di dalam ruangan.
Ketika pasukan darat Israel maju ke Gaza tengah pada bulan Desember, kedua keluarga muda tersebut menuju ke kota paling selatan Gaza, Rafah, yang sekarang menjadi rumah bagi ratusan ribu warga Palestina yang terlantar.
Seperti banyak orang yang mengungsi di Rafah yang penuh sesak, keluarga Al-Taweel tinggal di tenda, tempat mereka tinggal selama lebih dari sebulan.
“Itu adalah pengalaman terburuk dalam hidup saya; kondisi terburuk yang pernah saya alami,” kata Amal Al-Taweel.
Israel sangat membatasi pengiriman bantuan berupa makanan, air, obat-obatan dan pasokan lainnya ke Gaza selama perang, yang dimulai dengan serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang.
Israel telah menimbulkan jumlah korban yang sangat besar: Lebih dari 33.000 warga Palestina telah terbunuh, sekitar dua pertiga dari mereka adalah wanita dan anak-anak, menurut pejabat kesehatan Palestina yang jumlah kematiannya tidak dapat dibedakan antara warga sipil dan pejuang. Serangan Israel telah mendorong Gaza ke dalam krisis kemanusiaan, menyebabkan lebih dari 80% penduduknya mengungsi dan menyebabkan lebih dari 1 juta orang di ambang kelaparan.
Ali, yang didiagnosis menderita gastroenteritis sebelum keluarganya melarikan diri ke Rafah, mengalami muntah-muntah dan diare kronis – tanda-tanda malnutrisi yang menurut badan kesehatan utama PBB kini umum terjadi pada satu dari setiap enam anak kecil di Gaza. Dia kekurangan berat badan, hanya 5 kilogram (11 pon).
“Saya bahkan tidak bisa memberi makan diri saya sendiri untuk memberi makan anak saya dengan benar,” kata Amal Al-Taweel. “Berat badan anak itu turun lebih banyak daripada kenaikannya.”
Orang tuanya khawatir dengan ruam di wajahnya, berusaha melindunginya dari paparan sinar matahari yang terus-menerus di dalam tenda.
Mustafa Al-Taweel menghabiskan waktu berbulan-bulan menunggu meja di kafe Kota Gaza untuk menabung makanan bayi, mainan, dan pakaian. Kini, dia tidak mampu membelikan putranya makanan paling sederhana sekalipun di Rafah. Perang telah menyebabkan kekurangan kebutuhan dasar, sehingga popok dan susu formula sulit ditemukan atau tidak terjangkau. Mereka harus bergantung pada makanan kaleng yang disediakan oleh PBB.
“Ayahnya bekerja setiap hari untuk memberinya susu, popok, dan banyak hal lain yang dia butuhkan,” kata Amal Al-Taweel. “Bahkan mainannya pun hilang. Tidak ada apa pun yang mampu kami berikan kepadanya.”
Karena membutuhkan bantuan, keluarga Al-Taweel memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Amal di Gaza tengah pada bulan Februari.
Tak jauh dari tempat tinggal keluarga Al-Taweels di Rafah, Masa dan orang tuanya menemukan tempat di kamp pengungsi Shaboura. Mereka tinggal di sebuah tenda yang dibuat pasangan itu dengan menjahit kantong tepung, kata Saqer.
Air berlumpur menggenang di sekitar tenda saat hujan, dan area tersebut selalu berbau kotoran. Melakukan apa pun termasuk mengantri, artinya perjalanan ke kamar mandi bisa memakan waktu berjam-jam.
Masa menjadi sakit. Kulitnya menjadi kekuningan dan sepertinya dia menderita demam terus-menerus, dengan keringat bercucuran di dahi kecilnya. Saqer mencoba menyusui tetapi tidak dapat memproduksi ASI karena dia juga kekurangan gizi. Luka muncul di payudaranya.
“Bahkan ketika saya menahan rasa sakit dan mencoba menyusui putri saya, yang diminumnya adalah darah, bukan susu,” katanya.
Putus asa, Saqer menjual paket bantuan yang diterima keluarganya dari PBB untuk membeli susu formula untuk Masa. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke Gaza tengah untuk mencari perawatan medis bagi putrinya, meninggalkan suaminya untuk mengurus tenda mereka dan berangkat dengan kereta yang ditarik keledai.
Kedua ibu tersebut mencoba peruntungan di rumah sakit Al-Aqsa begitu mereka tiba di Gaza tengah. Saqer beruntung – dokter di sana memberi tahu dia bahwa Masa mengidap virus dan memberikan obat kepada bayinya.
Namun mereka memberi tahu Amal bahwa Ali memerlukan operasi hernia yang tidak dapat mereka lakukan. Seperti kebanyakan rumah sakit Gaza lainnya, Al-Aqsa hanya melakukan operasi penyelamatan jiwa. Setelah hampir enam bulan perang, sektor kesehatan di Gaza telah hancur. Hanya 10 dari 36 rumah sakit di Gaza yang masih berfungsi sebagian. Sisanya telah ditutup atau hampir tidak berfungsi karena kehabisan bahan bakar dan obat-obatan, digerebek oleh pasukan Israel atau dirusak oleh pertempuran.
Saat para keluarga memikirkan masa depan, mereka tidak dapat membayangkan bahwa kehidupan bayi mereka akan mendekati apa yang mereka bayangkan. Saqer mengatakan bahwa meskipun keluarganya dapat kembali ke rumah mereka di Gaza utara, mereka hanya akan menemukan puing-puing di tempat rumah mereka dulu berdiri.
“Hal yang sama juga saya derita di Rafah; Saya akan menderita di wilayah utara,” katanya. “Seluruh hidup kami akan dihabiskan di tenda. Ini tentu akan menjadi kehidupan yang sulit.”
Lihat Juga: Israel Klaim Rumah Sakit Al-Aqsa Tempat Komando Hamas, Peperangan di Wilayah Sipil Meningkat
Air ketuban Rola Saqer pecah hari itu ketika dia berlindung dari serangan udara Israel di Beit Lahia, sebuah kota Gaza dekat tempat militan Hamas melintasi perbatasan beberapa jam sebelumnya dalam serangan yang mengawali perang. Dia dan suaminya, Mohammed Zaqout, telah berusaha untuk memiliki anak selama lima tahun, dan bahkan ledakan mengerikan di sekitarnya tidak menghentikan mereka untuk pergi ke rumah sakit untuk melahirkan bayi mereka malam itu. Saqer melahirkan Masa, nama yang berarti berlian dalam bahasa Arab.
Keluarga-keluarga muncul dari rumah sakit menuju dunia yang berubah. Pada hari kedua kehidupan bayi-bayi tersebut, Israel menyatakan perang terhadap Hamas dan jet tempurnya menyerbu lingkungan tempat Ali dan Masa seharusnya dibesarkan. Dalam enam bulan sejak anak-anak mereka lahir, pasangan tersebut telah mengalami cobaan sebagai orang tua dini dengan latar belakang konflik brutal.
Rumah-rumah keluarga tersebut rata dengan serangan udara, dan mereka tidak memiliki tempat berlindung yang dapat diandalkan serta sedikit akses terhadap perawatan medis dan perlengkapan bayi. Bayi-bayi tersebut kelaparan, dan terlepas dari semua rencana yang dibuat oleh pasangan tersebut sebelum perang, mereka khawatir nyawa yang mereka harapkan untuk diberikan kepada anak-anak mereka akan hilang.
“Saya sedang mempersiapkannya untuk kehidupan lain, kehidupan yang indah, namun perang mengubah semua hal ini,” kata Amal Al-Taweel kepada The Associated Press. “Kami hampir tidak menjalani hidup hari demi hari, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada perencanaan.”
Saqer mengingat kembali harapannya sebelum perang.
“Ini putriku satu-satunya,” katanya sambil mengayunkan Masa dengan lembut dalam buaiannya. “Saya menyiapkan banyak barang dan pakaian untuknya. Saya membelikannya lemari seminggu sebelum perang. Saya juga merencanakan ulang tahunnya dan segalanya. Perang datang dan menghancurkan segalanya.”
Keluarga Al-Taweel menghabiskan hari-hari pertama kehidupan Ali berpindah-pindah rumah dan rumah kerabatnya untuk mencari keselamatan. Gedung-gedung di dekatnya terus dihantam – pertama di sebelah rumah saudara perempuan Amal, dan kemudian di sebelah rumah orang tuanya.
Ketika keluarga tersebut berlindung di rumah pada tanggal 20 Oktober, pihak berwenang Israel mengeluarkan perintah evakuasi yang memperingatkan bahwa serangan akan segera terjadi dan penduduk memiliki waktu 10 menit untuk pergi.
“Saya harus mengungsi. Saya tidak dapat menerima apa pun; tidak ada tanda pengenal, tidak ada ijazah universitas, tidak ada pakaian untuk anak saya – tidak ada apa-apa,” kata Amal Al-Taweel. “Bahkan susu, popok, dan mainan yang saya belikan untuk anak saya.”
Keluarga tersebut mencari perlindungan sementara di rumah orang tua Amal di Gaza tengah, di mana 15 anggota keluarga mengungsi.
Tak jauh dari situ, Saqer, suami dan putrinya berdesakan di rumah seorang kerabat dengan dua kamar tidur yang dihuni lebih dari 80 anggota keluarga besarnya. Saking ramainya, katanya, kerabat laki-lakinya membangun tenda di luar agar perempuan dan anak-anak bisa tidur lebih nyaman di dalam ruangan.
Ketika pasukan darat Israel maju ke Gaza tengah pada bulan Desember, kedua keluarga muda tersebut menuju ke kota paling selatan Gaza, Rafah, yang sekarang menjadi rumah bagi ratusan ribu warga Palestina yang terlantar.
Seperti banyak orang yang mengungsi di Rafah yang penuh sesak, keluarga Al-Taweel tinggal di tenda, tempat mereka tinggal selama lebih dari sebulan.
“Itu adalah pengalaman terburuk dalam hidup saya; kondisi terburuk yang pernah saya alami,” kata Amal Al-Taweel.
Israel sangat membatasi pengiriman bantuan berupa makanan, air, obat-obatan dan pasokan lainnya ke Gaza selama perang, yang dimulai dengan serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang.
Israel telah menimbulkan jumlah korban yang sangat besar: Lebih dari 33.000 warga Palestina telah terbunuh, sekitar dua pertiga dari mereka adalah wanita dan anak-anak, menurut pejabat kesehatan Palestina yang jumlah kematiannya tidak dapat dibedakan antara warga sipil dan pejuang. Serangan Israel telah mendorong Gaza ke dalam krisis kemanusiaan, menyebabkan lebih dari 80% penduduknya mengungsi dan menyebabkan lebih dari 1 juta orang di ambang kelaparan.
Ali, yang didiagnosis menderita gastroenteritis sebelum keluarganya melarikan diri ke Rafah, mengalami muntah-muntah dan diare kronis – tanda-tanda malnutrisi yang menurut badan kesehatan utama PBB kini umum terjadi pada satu dari setiap enam anak kecil di Gaza. Dia kekurangan berat badan, hanya 5 kilogram (11 pon).
“Saya bahkan tidak bisa memberi makan diri saya sendiri untuk memberi makan anak saya dengan benar,” kata Amal Al-Taweel. “Berat badan anak itu turun lebih banyak daripada kenaikannya.”
Orang tuanya khawatir dengan ruam di wajahnya, berusaha melindunginya dari paparan sinar matahari yang terus-menerus di dalam tenda.
Mustafa Al-Taweel menghabiskan waktu berbulan-bulan menunggu meja di kafe Kota Gaza untuk menabung makanan bayi, mainan, dan pakaian. Kini, dia tidak mampu membelikan putranya makanan paling sederhana sekalipun di Rafah. Perang telah menyebabkan kekurangan kebutuhan dasar, sehingga popok dan susu formula sulit ditemukan atau tidak terjangkau. Mereka harus bergantung pada makanan kaleng yang disediakan oleh PBB.
“Ayahnya bekerja setiap hari untuk memberinya susu, popok, dan banyak hal lain yang dia butuhkan,” kata Amal Al-Taweel. “Bahkan mainannya pun hilang. Tidak ada apa pun yang mampu kami berikan kepadanya.”
Karena membutuhkan bantuan, keluarga Al-Taweel memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Amal di Gaza tengah pada bulan Februari.
Tak jauh dari tempat tinggal keluarga Al-Taweels di Rafah, Masa dan orang tuanya menemukan tempat di kamp pengungsi Shaboura. Mereka tinggal di sebuah tenda yang dibuat pasangan itu dengan menjahit kantong tepung, kata Saqer.
Air berlumpur menggenang di sekitar tenda saat hujan, dan area tersebut selalu berbau kotoran. Melakukan apa pun termasuk mengantri, artinya perjalanan ke kamar mandi bisa memakan waktu berjam-jam.
Masa menjadi sakit. Kulitnya menjadi kekuningan dan sepertinya dia menderita demam terus-menerus, dengan keringat bercucuran di dahi kecilnya. Saqer mencoba menyusui tetapi tidak dapat memproduksi ASI karena dia juga kekurangan gizi. Luka muncul di payudaranya.
“Bahkan ketika saya menahan rasa sakit dan mencoba menyusui putri saya, yang diminumnya adalah darah, bukan susu,” katanya.
Putus asa, Saqer menjual paket bantuan yang diterima keluarganya dari PBB untuk membeli susu formula untuk Masa. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke Gaza tengah untuk mencari perawatan medis bagi putrinya, meninggalkan suaminya untuk mengurus tenda mereka dan berangkat dengan kereta yang ditarik keledai.
Kedua ibu tersebut mencoba peruntungan di rumah sakit Al-Aqsa begitu mereka tiba di Gaza tengah. Saqer beruntung – dokter di sana memberi tahu dia bahwa Masa mengidap virus dan memberikan obat kepada bayinya.
Namun mereka memberi tahu Amal bahwa Ali memerlukan operasi hernia yang tidak dapat mereka lakukan. Seperti kebanyakan rumah sakit Gaza lainnya, Al-Aqsa hanya melakukan operasi penyelamatan jiwa. Setelah hampir enam bulan perang, sektor kesehatan di Gaza telah hancur. Hanya 10 dari 36 rumah sakit di Gaza yang masih berfungsi sebagian. Sisanya telah ditutup atau hampir tidak berfungsi karena kehabisan bahan bakar dan obat-obatan, digerebek oleh pasukan Israel atau dirusak oleh pertempuran.
Saat para keluarga memikirkan masa depan, mereka tidak dapat membayangkan bahwa kehidupan bayi mereka akan mendekati apa yang mereka bayangkan. Saqer mengatakan bahwa meskipun keluarganya dapat kembali ke rumah mereka di Gaza utara, mereka hanya akan menemukan puing-puing di tempat rumah mereka dulu berdiri.
“Hal yang sama juga saya derita di Rafah; Saya akan menderita di wilayah utara,” katanya. “Seluruh hidup kami akan dihabiskan di tenda. Ini tentu akan menjadi kehidupan yang sulit.”
Lihat Juga: Israel Klaim Rumah Sakit Al-Aqsa Tempat Komando Hamas, Peperangan di Wilayah Sipil Meningkat
(ahm)