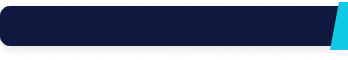Myanmar Berusaha Hapus Semua Sejarah Rohingya

Myanmar Berusaha Hapus Semua Sejarah Rohingya
A
A
A
SITTWE - Myanmar, melalui sebuah kampanye militer, tengah berusaha untuk menghilangkan bukti sejarah tentang Rohingya. Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas hak asasi manusia.
"Pasukan keamanan Myanmar telah berusaha untuk secara efektif untuk menghapus semua tanda geografis yang menunjukkan lanskap dan memori tentang Rohingya sedemikian rupa sehingga kembalinya mereka tidak akan menghasilkan apa-apa selain medan yang terpencil dan tak dapat dikenali," bunyi laporan uarkan pada bulan Oktober, Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.
Laporan PBB juga mengatakan bahwa tindakan keras di Rakhine telah menargetkan para guru, pemimpin budaya dan agama. Aksi itu juga mengincar orang-orang berpengaruh lainnya di komunitas Rohingya dalam upaya mengurangi sejarah, budaya dan pengetahuan Rohingya.
"Kami adalah orang-orang dengan sejarah dan tradisi kami sendiri," kata U Kyaw Hla Aung, seorang pengacara Rohingya dan mantan tahanan politik, yang ayahnya bertugas sebagai pegawai pengadilan di Sittwe, ibu kota Rakhine.
"Bagaimana mereka bisa berpura-pura kita bukan apa-apa?" tanyanya seperti disitir dari New York Times, Minggu (3/12/2017).
Berbicara melalui telepon, Kyaw Hla Aung mengatakan bahwa keluarganya tidak memiliki cukup makanan karena pejabat telah mencegah distribusi bantuan internasional secara penuh. Aung sendiri telah dipenjara berkali-kali karena aktivismenya dan sekarang diasingkan di sebuah kamp Sittwe.
Amnesia Myanmar yang tiba-tiba tentang Rohingya sama beraninya dengan penghapusan sejarah Rohingya secara sistematik.
Lima tahun yang lalu, Sittwe, yang terletak di muara di Teluk Benggala, adalah kota campuran, terbagi antara mayoritas etnis Rakhine Buddha dan minoritas Muslim Rohingya. Tapi sejak kerusuhan sektarian di tahun 2012, yang mengakibatkan jumlah korban Rohingya yang tidak proporsional, kota ini sebagian besar telah dibersihkan dari umat Islam. Di seberang pusat Rakhine, sekitar 120 ribu orang Rohingya, bahkan mereka yang memiliki kewarganegaraan, telah diasingkan di kamp-kamp, kehilangan mata pencaharian mereka dan dicegah untuk mengakses sekolah atau perawatan kesehatan yang tepat.
Mereka tidak bisa meninggalkan ghetto tanpa izin resmi. Pada bulan Juli, seorang pria Rohingya yang diijinkan masuk ke pengadilan di Sittwe digantung oleh sekelompok etnis Rakhine. Masjid Jama sekarang tidak digunakan lagi dan telah luluh lantak, di belakang kawat berduri. Imam Masjid yang berusia 89 tahun telah diasingkan.
"Kami tidak memiliki hak sebagai manusia. Ini adalah pembersihan etnis yang dilakukan negara dan tidak ada yang lain," kata sang Imam Masjid, meminta untuk tidak menggunakan namanya karena masalah keamanan.
Psikologis Sittwe pun telah menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Di sebuah bazar baru-baru ini, setiap penduduk Rakhine yang diajak bicara, mengklaim secara keliru, bahwa tidak ada seorang Muslim yang pernah memiliki toko di sana.
Sittwe University, yang biasa mendaftarkan ratusan siswa Muslim, sekarang hanya mengajar sekitar 30 Rohingya, semuanya berada dalam program pembelajaran jarak jauh.
"Kami tidak memiliki batasan terhadap agama apapun. Tapi mereka tidak datang," kata U Shwe Khaing Kyaw, administrasi universitas tersebut.
U Kyaw Min dulu mengajar di Sittwe, di mana sebagian besar muridnya adalah umat Buddha Rakhine. Sekarang, katanya, bahkan kenalannya yang beragama Buddha di Yangon merasa malu untuk berbicara dengannya.
"Mereka ingin percakapan segera berakhir karena mereka tidak ingin memikirkan siapa saya atau dari mana asalku," katanya.
Pada tahun 1990, Kyaw Min memenangkan kursi di Parlemen sebagai bagian dari partai Rohingya yang selaras dengan Liga Nasional untuk Demokrasi, partai pemerintahan Myanmar saat ini. Namun junta militer negara tersebut mengabaikan hasil pemilihan secara nasional. Kyaw Min berakhir di penjara.
Muslim Rohingya telah tinggal di Rakhine selama beberapa generasi, dialek Bengali dan Asia Selatan mereka sering membedakan mereka dari umat Buddha Rakhine.
Selama era kolonial, Inggris mendorong petani beras Asia Selatan, pedagang dan pegawai negeri sipil untuk bermigrasi ke tempat yang kemudian dikenal sebagai Birma.
Beberapa pendatang baru ini bercampur dengan Rohingya, yang kemudian dikenal lebih umum sebagai orang India Arakan atau Muslim Arakan. Yang lainnya tersebar di Burma. Pada tahun 1930-an, orang Asia Selatan, baik Muslim dan Hindu, terdiri dari populasi terbesar di Yangon.
Pergeseran demografis membuat beberapa umat Buddha merasa terkepung. Selama kepemimpinan xenophobia dari Jenderal Ne Win, yang mengantarkan hampir setengah abad pemerintahan militer, ratusan ribu orang Asia Selatan meninggalkan Burma ke India.
Rakhine, di pinggiran barat Burma, adalah tempat Islam dan Buddha bertabrakan paling keras, terutama setelah Perang Dunia II, di mana Rakhine mendukung Axis dan Rohingya the Allies.
Kemudian upaya oleh kelompok pemberontak Rohingya untuk keluar dari Burma dan melampirkan Rakhine utara ke Pakistan Timur, seperti yang diketahui Bangladesh, hubungan yang semakin tegang.
Pada tahun 1980-an, junta militer telah melucuti sebagian besar kewarganegaraan Rohingya. Serangan keamanan brutal membuat gelombang Rohingya melarikan diri dari negara tersebut.
Hari ini, jauh lebih banyak Rohingya tinggal di luar Myanmar - kebanyakan di Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi dan Malaysia - daripada tetap berada di tempat yang mereka anggap sebagai tanah air mereka.
Namun pada dasawarsa awal kemerdekaan Burma, elite Rohingya berkembang pesat. Universitas Rangoon, institusi tertinggi di negara itu, memiliki cukup banyak siswa Rohingya untuk membentuk serikat mereka sendiri. Salah satu kabinet U Nu, pemimpin pasca kemerdekaan pertama negara tersebut, termasuk seorang menteri kesehatan yang mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim Arakan.
Bahkan di bawah Ne Win, radio nasional Burma yang umum menyiarkan siaran dalam bahasa Rohingya. Rohingya, perempuan di antara mereka, diwakili di Parlemen.
U Shwe Maung, seorang Rohingya dari Kotapraja Buthidaung di Rakhine utara, bertugas di Parlemen antara tahun 2011 dan 2015, sebagai anggota partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan Persatuan Militer. Namun, dalam pemilihan 2015, dia dilarang ikut.
Ratusan ribu orang Rohingya dicabut haknya dalam pemilihan tersebut.
Distrik pemilihan Shwe Maung, yang dihuni 90 persen Rohingya, sekarang diwakili oleh seorang Buddha Rakhine. Pada bulan September, seorang perwira polisi setempat mengajukan tuntutan kontraterorisme yang menuduh Shwe Maung menghasut kekerasan melalui postingan di Facebook yang menyerukan diakhirinya serangan keamanan di Rakhine.
Shwe Maung, anak seorang perwira polisi, berada di pengasingan di Amerika Serikat dan membantah tuduhan tersebut.
"Mereka ingin setiap Rohingya dianggap teroris atau imigran ilegal. Kami lebih dari itu," katanya.
"Pasukan keamanan Myanmar telah berusaha untuk secara efektif untuk menghapus semua tanda geografis yang menunjukkan lanskap dan memori tentang Rohingya sedemikian rupa sehingga kembalinya mereka tidak akan menghasilkan apa-apa selain medan yang terpencil dan tak dapat dikenali," bunyi laporan uarkan pada bulan Oktober, Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.
Laporan PBB juga mengatakan bahwa tindakan keras di Rakhine telah menargetkan para guru, pemimpin budaya dan agama. Aksi itu juga mengincar orang-orang berpengaruh lainnya di komunitas Rohingya dalam upaya mengurangi sejarah, budaya dan pengetahuan Rohingya.
"Kami adalah orang-orang dengan sejarah dan tradisi kami sendiri," kata U Kyaw Hla Aung, seorang pengacara Rohingya dan mantan tahanan politik, yang ayahnya bertugas sebagai pegawai pengadilan di Sittwe, ibu kota Rakhine.
"Bagaimana mereka bisa berpura-pura kita bukan apa-apa?" tanyanya seperti disitir dari New York Times, Minggu (3/12/2017).
Berbicara melalui telepon, Kyaw Hla Aung mengatakan bahwa keluarganya tidak memiliki cukup makanan karena pejabat telah mencegah distribusi bantuan internasional secara penuh. Aung sendiri telah dipenjara berkali-kali karena aktivismenya dan sekarang diasingkan di sebuah kamp Sittwe.
Amnesia Myanmar yang tiba-tiba tentang Rohingya sama beraninya dengan penghapusan sejarah Rohingya secara sistematik.
Lima tahun yang lalu, Sittwe, yang terletak di muara di Teluk Benggala, adalah kota campuran, terbagi antara mayoritas etnis Rakhine Buddha dan minoritas Muslim Rohingya. Tapi sejak kerusuhan sektarian di tahun 2012, yang mengakibatkan jumlah korban Rohingya yang tidak proporsional, kota ini sebagian besar telah dibersihkan dari umat Islam. Di seberang pusat Rakhine, sekitar 120 ribu orang Rohingya, bahkan mereka yang memiliki kewarganegaraan, telah diasingkan di kamp-kamp, kehilangan mata pencaharian mereka dan dicegah untuk mengakses sekolah atau perawatan kesehatan yang tepat.
Mereka tidak bisa meninggalkan ghetto tanpa izin resmi. Pada bulan Juli, seorang pria Rohingya yang diijinkan masuk ke pengadilan di Sittwe digantung oleh sekelompok etnis Rakhine. Masjid Jama sekarang tidak digunakan lagi dan telah luluh lantak, di belakang kawat berduri. Imam Masjid yang berusia 89 tahun telah diasingkan.
"Kami tidak memiliki hak sebagai manusia. Ini adalah pembersihan etnis yang dilakukan negara dan tidak ada yang lain," kata sang Imam Masjid, meminta untuk tidak menggunakan namanya karena masalah keamanan.
Psikologis Sittwe pun telah menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Di sebuah bazar baru-baru ini, setiap penduduk Rakhine yang diajak bicara, mengklaim secara keliru, bahwa tidak ada seorang Muslim yang pernah memiliki toko di sana.
Sittwe University, yang biasa mendaftarkan ratusan siswa Muslim, sekarang hanya mengajar sekitar 30 Rohingya, semuanya berada dalam program pembelajaran jarak jauh.
"Kami tidak memiliki batasan terhadap agama apapun. Tapi mereka tidak datang," kata U Shwe Khaing Kyaw, administrasi universitas tersebut.
U Kyaw Min dulu mengajar di Sittwe, di mana sebagian besar muridnya adalah umat Buddha Rakhine. Sekarang, katanya, bahkan kenalannya yang beragama Buddha di Yangon merasa malu untuk berbicara dengannya.
"Mereka ingin percakapan segera berakhir karena mereka tidak ingin memikirkan siapa saya atau dari mana asalku," katanya.
Pada tahun 1990, Kyaw Min memenangkan kursi di Parlemen sebagai bagian dari partai Rohingya yang selaras dengan Liga Nasional untuk Demokrasi, partai pemerintahan Myanmar saat ini. Namun junta militer negara tersebut mengabaikan hasil pemilihan secara nasional. Kyaw Min berakhir di penjara.
Muslim Rohingya telah tinggal di Rakhine selama beberapa generasi, dialek Bengali dan Asia Selatan mereka sering membedakan mereka dari umat Buddha Rakhine.
Selama era kolonial, Inggris mendorong petani beras Asia Selatan, pedagang dan pegawai negeri sipil untuk bermigrasi ke tempat yang kemudian dikenal sebagai Birma.
Beberapa pendatang baru ini bercampur dengan Rohingya, yang kemudian dikenal lebih umum sebagai orang India Arakan atau Muslim Arakan. Yang lainnya tersebar di Burma. Pada tahun 1930-an, orang Asia Selatan, baik Muslim dan Hindu, terdiri dari populasi terbesar di Yangon.
Pergeseran demografis membuat beberapa umat Buddha merasa terkepung. Selama kepemimpinan xenophobia dari Jenderal Ne Win, yang mengantarkan hampir setengah abad pemerintahan militer, ratusan ribu orang Asia Selatan meninggalkan Burma ke India.
Rakhine, di pinggiran barat Burma, adalah tempat Islam dan Buddha bertabrakan paling keras, terutama setelah Perang Dunia II, di mana Rakhine mendukung Axis dan Rohingya the Allies.
Kemudian upaya oleh kelompok pemberontak Rohingya untuk keluar dari Burma dan melampirkan Rakhine utara ke Pakistan Timur, seperti yang diketahui Bangladesh, hubungan yang semakin tegang.
Pada tahun 1980-an, junta militer telah melucuti sebagian besar kewarganegaraan Rohingya. Serangan keamanan brutal membuat gelombang Rohingya melarikan diri dari negara tersebut.
Hari ini, jauh lebih banyak Rohingya tinggal di luar Myanmar - kebanyakan di Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi dan Malaysia - daripada tetap berada di tempat yang mereka anggap sebagai tanah air mereka.
Namun pada dasawarsa awal kemerdekaan Burma, elite Rohingya berkembang pesat. Universitas Rangoon, institusi tertinggi di negara itu, memiliki cukup banyak siswa Rohingya untuk membentuk serikat mereka sendiri. Salah satu kabinet U Nu, pemimpin pasca kemerdekaan pertama negara tersebut, termasuk seorang menteri kesehatan yang mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim Arakan.
Bahkan di bawah Ne Win, radio nasional Burma yang umum menyiarkan siaran dalam bahasa Rohingya. Rohingya, perempuan di antara mereka, diwakili di Parlemen.
U Shwe Maung, seorang Rohingya dari Kotapraja Buthidaung di Rakhine utara, bertugas di Parlemen antara tahun 2011 dan 2015, sebagai anggota partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan Persatuan Militer. Namun, dalam pemilihan 2015, dia dilarang ikut.
Ratusan ribu orang Rohingya dicabut haknya dalam pemilihan tersebut.
Distrik pemilihan Shwe Maung, yang dihuni 90 persen Rohingya, sekarang diwakili oleh seorang Buddha Rakhine. Pada bulan September, seorang perwira polisi setempat mengajukan tuntutan kontraterorisme yang menuduh Shwe Maung menghasut kekerasan melalui postingan di Facebook yang menyerukan diakhirinya serangan keamanan di Rakhine.
Shwe Maung, anak seorang perwira polisi, berada di pengasingan di Amerika Serikat dan membantah tuduhan tersebut.
"Mereka ingin setiap Rohingya dianggap teroris atau imigran ilegal. Kami lebih dari itu," katanya.
(ian)