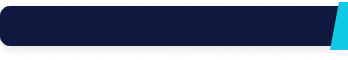Pakar: Ekonomi Jatuh, Era Arab Saudi Berduit Berakhir
loading...

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Putra Mahkota Mohammad bin Salman dari Kerajaan Arab Saudi. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Para pakar Barat meyakini era Arab Saudi sebagai negara Teluk yang memiliki banyak uang telah berakhir seiring dengan jatuhnya ekonomi negara itu yang dipicu anjloknya harga minyak dan diperparah oleh pandemi Covid-19. Menurut mereka, krisis ini juga akan memaksa Riyadh menunda pembelian senjata.
Penundaan pembelian senjata baru dapat memiliki dampak politik jangka panjang bagi negara di bawah pemerintahan Mohammed bin Salman—Putra Mahkota dan penguasa de facto yang telah melancarkan perang berdarah di Yaman.
“Saya tidak ragu, ini adalah akhir dari suatu era. Era Teluk Persia memiliki semua uang ini berakhir," kata Bruce Riedel, seorang pakar senior di Brookings Institution di Washington dan veteran dari Central Intelligence Agency (CIA), yang telah bekerja sebagai penasihat masalah-masalah Timur Tengah di beberapa administrasi AS.
Arab Saudi menghabiskan sekitar USD62 miliar untuk impor senjata pada tahun lalu, menjadikannya pemboros kelima terbesar di dunia untuk pembelian senjata. Meskipun angka itu kurang dari data belanja pada tahun 2018, namun masih mewakili sekitar 8 persen dari PDB Arab Saudi, yang berarti bahwa negara tersebut menghabiskan sebagian besar kekayaannya untuk senjata daripada Amerika Serikat (3,4%), China (1,9%), Rusia (3,9%), atau India (2,4%).
"Jika Arab Saudi bukan salah satu pembeli senjata terbesar, Anda mungkin tidak dapat mengandalkan dukungan kritis dari kekuatan Barat yang kuat. Salah satu hasil dari pembelian senjata adalah Anda membeli hubungan," kata Andrew Feinstein, seorang ahli korupsi dan perdagangan senjata global.
Di AS, Donald Trump di masa lalu menunjuk pada pembelian senjata yang diajukan Arab Saudi—dan melambungkan perkiraan tentang dampaknya terhadap pekerjaan AS—untuk membenarkan tanggapan lunak pemerintahannya terhadap pembunuhan Jamal Khashoggi, jurnalis Washington Post. (Baca: Ekonomi Arab Saudi Jatuh, Pakar Prediksi Biaya Haji Naik Lebih Mahal )
Inggris menjual lebih banyak senjata ke Arab Saudi daripada ke negara lain—lebih dari £4,7 miliar sejak kerajaan tersebut memulai kampanye pemboman terhadap Yaman pada Maret 2015—dan Perdana Menteri Boris Johnson telah menghadapi kritik karena membiarkan penjualan senjata terus berlanjut meskipun ada kekhawatiran bahwa Inggris mengambil risiko melanggar hukum humaniter internasional dengan membantu aksi Saudi.
Tetapi Riedel dan pakar lainnya percaya bahwa pemerintah Arab Saudi akan memiliki banyak pilihan selain menunda pengeluaran militer, dalam beberapa kasus secara permanen.
Andrew Smith, pakar di Kampanye Anti-Perdagangan Senjata, mengatakan; “Saya berharap mereka dalam jangka pendek menunda melakukan beberapa pembelian yang lebih besar, seperti seperangkat jet tempur baru, misalnya, yang telah dinegosiasikan oleh Inggris untuk beberapa waktu."
Pakar lain, Gerald Feierstein, mantan duta besar AS untuk Yaman, mengatakan akan mudah bagi Arab Saudi untuk menunda atau membatalkan kontrak senjata baru, tetapi pemerintah Saudi kemungkinan akan harus melanjutkan kontrak perawatan untuk menjaga agar pasukannya saat ini dapat dioperasikan. Feierstein mengatakan Arab Saudi di masa lalu telah berusaha untuk menegosiasikan kembali jadwal pembayaran untuk senjata, memperpanjang pembayaran dalam jangka waktu yang lama.
"Ingat ketika Mohammed bin Salman datang ke Gedung Putih dan Trump mengangkat grafik kardus dengan penjualan USD100 miliar, itu semua tetap aspiratif," kata Feierstein. "Sebagian besar dari hal-hal itu tidak pernah terjadi dan itu tidak pernah ditandatangani, itu hanya semacam ditarik keluar dari udara," kata Feierstein.
Pangeran Mohammed tidak hanya memiliki krisis keuangan yang perlu dikhawatirkan. Di AS, dia menghadapi prospek Joe Biden—calon calon presiden dari Partai Demokrat—menang pada pemilu AS November mendatang. Biden telah mengatakan dia akan mengekang penjualan senjata AS ke Arab Saudi dan menyebut kepemimpinan Riyadh saat ini sebagai "paria".
"Saya benar-benar berpikir bahwa (krisis keuangan) akan memengaruhi semua pengeluaran mereka," kata Kirsten Fontenrose, yang menjabat sebagai direktur senior untuk urusan Teluk di Dewan Keamanan Nasional di pemerintahan Trump.
Alih-alih menyerukan pemotongan pengeluaran, Fontenrose menyarankan Saudi untuk menunggu hasil pemilu AS November mendatang dan—jika Biden menang—bagi Demokrat untuk memaksakan pengurangan belanja, yang mereka “pura-pura menerima dengan enggan”.
"Itu akan menjadi cara bagi mereka untuk melepaskan diri dari dampak politik dan mempertahankan beberapa pengaruh mereka dengan sektor swasta," katanya.
Sementara itu, Riedel mengatakan bahwa di antara perusahaan-perusahaan yang paling terpukul adalah BAE Systems Inggris, mengingat eksposur perusahaan ke Arab Saudi.
“BAE akan sangat terpukul. Ada ribuan karyawan BAE yang pekerjaannya berputar mendukung Angkatan Udara Saudi dengan satu atau lain cara. Cepat atau lambat mereka akan diberitahu 'kami tidak dapat membayar gaji Anda lagi'," katanya, seperti dikutip The Guardian, Senin (18/5/2020).
Lihat Juga: 5 Tanda Kiamat yang Muncul dari Mekkah, dari Gunung Berlubang hingga Bayangan Kabah Tidak Terlihat
Penundaan pembelian senjata baru dapat memiliki dampak politik jangka panjang bagi negara di bawah pemerintahan Mohammed bin Salman—Putra Mahkota dan penguasa de facto yang telah melancarkan perang berdarah di Yaman.
“Saya tidak ragu, ini adalah akhir dari suatu era. Era Teluk Persia memiliki semua uang ini berakhir," kata Bruce Riedel, seorang pakar senior di Brookings Institution di Washington dan veteran dari Central Intelligence Agency (CIA), yang telah bekerja sebagai penasihat masalah-masalah Timur Tengah di beberapa administrasi AS.
Arab Saudi menghabiskan sekitar USD62 miliar untuk impor senjata pada tahun lalu, menjadikannya pemboros kelima terbesar di dunia untuk pembelian senjata. Meskipun angka itu kurang dari data belanja pada tahun 2018, namun masih mewakili sekitar 8 persen dari PDB Arab Saudi, yang berarti bahwa negara tersebut menghabiskan sebagian besar kekayaannya untuk senjata daripada Amerika Serikat (3,4%), China (1,9%), Rusia (3,9%), atau India (2,4%).
"Jika Arab Saudi bukan salah satu pembeli senjata terbesar, Anda mungkin tidak dapat mengandalkan dukungan kritis dari kekuatan Barat yang kuat. Salah satu hasil dari pembelian senjata adalah Anda membeli hubungan," kata Andrew Feinstein, seorang ahli korupsi dan perdagangan senjata global.
Di AS, Donald Trump di masa lalu menunjuk pada pembelian senjata yang diajukan Arab Saudi—dan melambungkan perkiraan tentang dampaknya terhadap pekerjaan AS—untuk membenarkan tanggapan lunak pemerintahannya terhadap pembunuhan Jamal Khashoggi, jurnalis Washington Post. (Baca: Ekonomi Arab Saudi Jatuh, Pakar Prediksi Biaya Haji Naik Lebih Mahal )
Inggris menjual lebih banyak senjata ke Arab Saudi daripada ke negara lain—lebih dari £4,7 miliar sejak kerajaan tersebut memulai kampanye pemboman terhadap Yaman pada Maret 2015—dan Perdana Menteri Boris Johnson telah menghadapi kritik karena membiarkan penjualan senjata terus berlanjut meskipun ada kekhawatiran bahwa Inggris mengambil risiko melanggar hukum humaniter internasional dengan membantu aksi Saudi.
Tetapi Riedel dan pakar lainnya percaya bahwa pemerintah Arab Saudi akan memiliki banyak pilihan selain menunda pengeluaran militer, dalam beberapa kasus secara permanen.
Andrew Smith, pakar di Kampanye Anti-Perdagangan Senjata, mengatakan; “Saya berharap mereka dalam jangka pendek menunda melakukan beberapa pembelian yang lebih besar, seperti seperangkat jet tempur baru, misalnya, yang telah dinegosiasikan oleh Inggris untuk beberapa waktu."
Pakar lain, Gerald Feierstein, mantan duta besar AS untuk Yaman, mengatakan akan mudah bagi Arab Saudi untuk menunda atau membatalkan kontrak senjata baru, tetapi pemerintah Saudi kemungkinan akan harus melanjutkan kontrak perawatan untuk menjaga agar pasukannya saat ini dapat dioperasikan. Feierstein mengatakan Arab Saudi di masa lalu telah berusaha untuk menegosiasikan kembali jadwal pembayaran untuk senjata, memperpanjang pembayaran dalam jangka waktu yang lama.
"Ingat ketika Mohammed bin Salman datang ke Gedung Putih dan Trump mengangkat grafik kardus dengan penjualan USD100 miliar, itu semua tetap aspiratif," kata Feierstein. "Sebagian besar dari hal-hal itu tidak pernah terjadi dan itu tidak pernah ditandatangani, itu hanya semacam ditarik keluar dari udara," kata Feierstein.
Pangeran Mohammed tidak hanya memiliki krisis keuangan yang perlu dikhawatirkan. Di AS, dia menghadapi prospek Joe Biden—calon calon presiden dari Partai Demokrat—menang pada pemilu AS November mendatang. Biden telah mengatakan dia akan mengekang penjualan senjata AS ke Arab Saudi dan menyebut kepemimpinan Riyadh saat ini sebagai "paria".
"Saya benar-benar berpikir bahwa (krisis keuangan) akan memengaruhi semua pengeluaran mereka," kata Kirsten Fontenrose, yang menjabat sebagai direktur senior untuk urusan Teluk di Dewan Keamanan Nasional di pemerintahan Trump.
Alih-alih menyerukan pemotongan pengeluaran, Fontenrose menyarankan Saudi untuk menunggu hasil pemilu AS November mendatang dan—jika Biden menang—bagi Demokrat untuk memaksakan pengurangan belanja, yang mereka “pura-pura menerima dengan enggan”.
"Itu akan menjadi cara bagi mereka untuk melepaskan diri dari dampak politik dan mempertahankan beberapa pengaruh mereka dengan sektor swasta," katanya.
Sementara itu, Riedel mengatakan bahwa di antara perusahaan-perusahaan yang paling terpukul adalah BAE Systems Inggris, mengingat eksposur perusahaan ke Arab Saudi.
“BAE akan sangat terpukul. Ada ribuan karyawan BAE yang pekerjaannya berputar mendukung Angkatan Udara Saudi dengan satu atau lain cara. Cepat atau lambat mereka akan diberitahu 'kami tidak dapat membayar gaji Anda lagi'," katanya, seperti dikutip The Guardian, Senin (18/5/2020).
Lihat Juga: 5 Tanda Kiamat yang Muncul dari Mekkah, dari Gunung Berlubang hingga Bayangan Kabah Tidak Terlihat
(min)