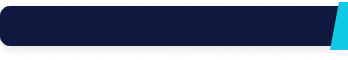Krisis Rohingya, DK PBB Didesak Jatuhkan Embargo Senjata ke Myanmar

Krisis Rohingya, DK PBB Didesak Jatuhkan Embargo Senjata ke Myanmar
A
A
A
WASHINGTON - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) didesak untuk menjatuhkan sanksi dan embargo senjata kepada militer Myanmar sebagai respons atas kekerasan yang dialami etnis Rohingya. PBB telah memperingatkan bahwa kekerasan di Rakhine bisa berpotensi pada pembersihan etnis.
Desakan embargo senjata diserukan kelompok HAM, Human Rights Watch (HRW). Kelompok ini menilai pasukan keamanan Myanmar telah mengabaikan kecaman para pemimpin dunia atas krisis Rohingya yang memaksa sekitar 410.000 warga muslim Rohingya eksodus ke Bangladesh.
Kekerasan terbaru pecah di negara bagian Rakhine atau Arakan, Myanmar sejak 25 Agustus 2017. Awalnya, kelompok gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang puluhan pos polisi dan markas militer yang menewaskan sekitar 12 petugas. Serangan ini memicu operasi militer besar-besaran di desa-desa Rohingya.
Pemerintah Myanmar telah mengakui ada 471 desa Rohingya yang jadi target operasi militer. Dari jumlah itu, 176 desa di antaranya kini benar-benar kosong.
Militer mengaku telah membunuh lebih dari 300 warga Rohingya yang mereka klaim anggota gerilyawan. Tapi, para para pengungsi yang selamat dan para aktivis menyatakan militer membantai banyak warga sipil. Citra satelit juga menunjukkan banyak desa dibakar.
Menurut HRW, waktunya telah tiba untuk menerapkan tindakan tegas yang tidak dapat diabaikan oleh jenderal-jenderal Myanmar.
”Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara yang bersangkutan harus menerapkan sanksi dan embargo senjata kepada militer Burma (Myanmar) untuk mengakhiri kampanye pembersihan etnisnya,” kata HRW dalam sebuah rilis, Senin (18/9/2017).
Sekitar satu juta Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine. Sebagian besar menghadapi pembatasan perjalanan yang kejam dan ditolak kewarganegaraannya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha tersebut. Pemerintah negara itu menganggap etnis Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Pemimpin de facto Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menghadapi serangkaian kecaman dari masyarakat internasional karena dianggap tidak berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan di negaranya.
Suu Kyi dijadwalkan menyampaikan pidato pertamanya kepada negara tersebut pada hari Selasa (19/9/2017) besok.
Amerika Serikat telah meminta perlindungan warga sipil Rohingya. Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Patrick Murphy dijadwalkan berada di Myanmar minggu ini. Dia akan pergi ke Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine, untuk bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan dari berbagai komunitas, termasuk perwakilan etnis Rohingya. Namun, dia tidak berusaha melakukan perjalanan ke zona konflik di negara bagian Rakhine utara.
“Human Rights Watch meminta pemerintah (AS) untuk memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap petugas keamanan yang terlibat dalam pelanggaran serius; memperluas embargo senjata termasuk semua penjualan (perlatan) militer, bantuan, dan kerja sama, dan melakukan pelarangan transaksi keuangan dengan (tokoh) kunci militer,” lanjut pernyataan HRW.
Selama bertahun-tahun, AS dan negara-negara Barat lainnya memberlakukan sanksi terhadap Myanmar yang bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan militer dan mendukung kampanye Suu Kyi untuk demokrasi. Namun, junta militer Myanmar memilih membangun hubungan yang lebih dekat dengan tetangganya, China.
Hubungan antara AS dan Myanmar telah membaik sejak militer mulai menarik diri dari jalannya pemerintahan negara tersebut pada tahun 2011. Langkah itu membuka jalan untuk pemilu 2015 yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Daw Aung San Suu Kyi.
Seorang pejabat administrasi Presiden Donald Trump mengatakan bahwa kekerasan tersebut membuat lebih sulit untuk membangun hubungan yang lebih hangat bagi kedua negara. Tapi, dia mengharapkan penjatuhan sanksi terhadap Myanmar.
”Orang-orang terlalu diinvestasikan dalam lima tahun terakhir pencairan (hubungan), yang dipahami oleh setiap orang agar menjadi suara yang strategis,” kata pejabat yang menolak untuk diidentifikasi tersebut, seperti dikutip Reuters. ”Jangka panjang, lintasannya mungkin hubungan yang lebih ketat.”
Desakan embargo senjata diserukan kelompok HAM, Human Rights Watch (HRW). Kelompok ini menilai pasukan keamanan Myanmar telah mengabaikan kecaman para pemimpin dunia atas krisis Rohingya yang memaksa sekitar 410.000 warga muslim Rohingya eksodus ke Bangladesh.
Kekerasan terbaru pecah di negara bagian Rakhine atau Arakan, Myanmar sejak 25 Agustus 2017. Awalnya, kelompok gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang puluhan pos polisi dan markas militer yang menewaskan sekitar 12 petugas. Serangan ini memicu operasi militer besar-besaran di desa-desa Rohingya.
Pemerintah Myanmar telah mengakui ada 471 desa Rohingya yang jadi target operasi militer. Dari jumlah itu, 176 desa di antaranya kini benar-benar kosong.
Militer mengaku telah membunuh lebih dari 300 warga Rohingya yang mereka klaim anggota gerilyawan. Tapi, para para pengungsi yang selamat dan para aktivis menyatakan militer membantai banyak warga sipil. Citra satelit juga menunjukkan banyak desa dibakar.
Menurut HRW, waktunya telah tiba untuk menerapkan tindakan tegas yang tidak dapat diabaikan oleh jenderal-jenderal Myanmar.
”Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara yang bersangkutan harus menerapkan sanksi dan embargo senjata kepada militer Burma (Myanmar) untuk mengakhiri kampanye pembersihan etnisnya,” kata HRW dalam sebuah rilis, Senin (18/9/2017).
Sekitar satu juta Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine. Sebagian besar menghadapi pembatasan perjalanan yang kejam dan ditolak kewarganegaraannya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha tersebut. Pemerintah negara itu menganggap etnis Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Pemimpin de facto Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menghadapi serangkaian kecaman dari masyarakat internasional karena dianggap tidak berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan di negaranya.
Suu Kyi dijadwalkan menyampaikan pidato pertamanya kepada negara tersebut pada hari Selasa (19/9/2017) besok.
Amerika Serikat telah meminta perlindungan warga sipil Rohingya. Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Patrick Murphy dijadwalkan berada di Myanmar minggu ini. Dia akan pergi ke Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine, untuk bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan dari berbagai komunitas, termasuk perwakilan etnis Rohingya. Namun, dia tidak berusaha melakukan perjalanan ke zona konflik di negara bagian Rakhine utara.
“Human Rights Watch meminta pemerintah (AS) untuk memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap petugas keamanan yang terlibat dalam pelanggaran serius; memperluas embargo senjata termasuk semua penjualan (perlatan) militer, bantuan, dan kerja sama, dan melakukan pelarangan transaksi keuangan dengan (tokoh) kunci militer,” lanjut pernyataan HRW.
Selama bertahun-tahun, AS dan negara-negara Barat lainnya memberlakukan sanksi terhadap Myanmar yang bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan militer dan mendukung kampanye Suu Kyi untuk demokrasi. Namun, junta militer Myanmar memilih membangun hubungan yang lebih dekat dengan tetangganya, China.
Hubungan antara AS dan Myanmar telah membaik sejak militer mulai menarik diri dari jalannya pemerintahan negara tersebut pada tahun 2011. Langkah itu membuka jalan untuk pemilu 2015 yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Daw Aung San Suu Kyi.
Seorang pejabat administrasi Presiden Donald Trump mengatakan bahwa kekerasan tersebut membuat lebih sulit untuk membangun hubungan yang lebih hangat bagi kedua negara. Tapi, dia mengharapkan penjatuhan sanksi terhadap Myanmar.
”Orang-orang terlalu diinvestasikan dalam lima tahun terakhir pencairan (hubungan), yang dipahami oleh setiap orang agar menjadi suara yang strategis,” kata pejabat yang menolak untuk diidentifikasi tersebut, seperti dikutip Reuters. ”Jangka panjang, lintasannya mungkin hubungan yang lebih ketat.”
(mas)