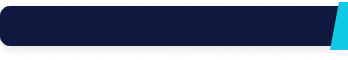Hati Bahagia Jika Ingat Medan, Bandung dan Palembang

Hati Bahagia Jika Ingat Medan, Bandung dan Palembang
A
A
A
BERANDA depan menghadap jalan beraspal yang tenteram. Halaman belakang dibatasi kebun anggur. Menguning daunnya karena musim gugur tiba. Tak sampai ratusan meter, dari kebun anggur itu, berdiri kokoh Kastil Spiez. Lalu ada danau biru nan bening, yakni Thun yang di tengahnya tampak kapal ferry penuh mengangkut turis domestik, sebagian lain dari China dan India.
Spiez, nama desa itu, memang menjadi salah satu desa tetirah di Berner Oberland, dataran tinggi Bern. Berner Oberland yang meliputi Interlaken, Lauterbrunnen serta Grindewald adalah high light kunjungan wisatawan ke Heidiland. Di tempat eksotik ini selain ada gunung, danau, dan ratusan air terjun juga sapi-sapi gemuk yang merumput di lembah hijau ala Swiss.
Di tempat inilah, Gladys Luginbuehl Surbek melewatkan masa tuanya. Usianya sudah sepuh, 93 tahun, tapi ingatannya masih jernih, terutama jika bicara tentang Indonesia, atau tepatnya Hindia Belanda. Matanya berbinar binar mengenang masa lalunya di Indonesia, antara Medan, Palembang dan Bandung. Ketiga tempat itulah yang menancap di hatinya hingga sekarang. “Kalau saya sedih atau saya sakit, saya tetap bisa bahagia jika mengingat masa kecil di Indonesia,“ katanya ketika ditemui KORAN SINDO di kediamannya, baru-baru ini.
Gladys memang warga Swiss yang menjadi saksi hidup zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Dia lahir dan besar hingga remaja di Sumatera dan Jawa Barat. Total di kota-kota sebelum Indonesia berdiri itu, dia tinggal selama 16 tahun. “Karena orang tua saya menjadi dokter di Indonesia,“ kenangnya. “Dokter yang bekerja untuk Kerajaan Belanda tepatnya,” timpalnya.
Orang tua Gladys itu bernama Kurt dan Gret Surbek, yang menjalankan tugasnya mulai 1919 di Batang Seponggol, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Namun selain di Batang Seponggol, Gladys juga sering ke Medan. Lalu orang tuanya pindah tugas ke Palembang, Bandung, Perth, Australia dan kembali ke Berner Oberland.
Gladys kini begitu sepuh. Dan, tidak semua mampu diingatnya. Namun catatan harian yang ditinggalkan Gret sebanyak 17 bundel, menjadikan kisah dramatis pasangan ini, termasuk Gladys dan Bernhard atau Bernie, kakaknya, terungkap.
Lewat sebuah buku, Im Herzen Waren Wir Indonesier (Di Dalam Hati Kami, Kami Orang Indonesia) dan sepotong film, Gladys Reise (Perjalanan Gladys), kisah dramatis ini kembali hidup. “Saya masih ingat betul, bagaimana kami dibebaskan oleh orang tua untuk bermain dengan anak kampung, sementara anak-anak orang putih lainnya, dilarang bermain dengan mereka,“ aku Gladys.
Kacung, kuli, jongos bahkan monyet menjadi sebutan umum orang Belanda bagi penduduk pribumi di zaman itu. Tapi Gladys sama sekali tidak melihatnya semacam itu. “Kami main kelereng biasanya, tanpa ada sekat sosial, “ katanya.
Keakraban dengan asisten rumah tangga, juga sangat membekas di hatinya. “Mereka sangat manis, sangat baik kepada kami,“ kata Gladys dengan mata berbinar.
Kurt dan Gret hanya memiliki dua anak. Jika Bernie dilahirkan di Swiss, Gladys lahir di sebuah klinik di Palembang. Kelahiran anak pertama pasangan ini, sengaja dilakukan di Swiss, lantaran belum percaya betul terhadap layanan kesehatan di Hindia Belanda zaman itu. Sementara Gladys dilahirkan di sebuah rumah sakit di Palembang.
Masa itu adalah masa kolonialisme Belanda. Semua orang kulit putih adalah warga negara kelas satu, diikuti warga Asia atau Arab. Adapun yang paling bawah adalah warga pribumi.
Lantaran orangtuanya dokter, kehidupan keluarga Surbek cukup istimewa, bahkan tergolong mewah. Tiap tahun, Kurt bisa berganti mobil. “Lebih baik ganti mobil baru ketimbang istri baru,“ tulis Gret dalam catatan hariannya.
Hobbi mewah Kurt lainnya adalah berburu binatang. Tidak hanya siamang, Kala itu Kurt juga berhasil merobohkan gajah dengan senapannya.
Pada akhirnya, Kurt dan Gret, tentu saja Gladys dan Bernie juga, pindah ke Bandung, Jawa Barat. Hampir sama dengan di Sumatera Utara, kehidupan keluarga ini juga masih mewah. Kurt bahkan mendirikan rumah sakit swasta di Lembang, Jawa Barat. Namanya Solsana, sebuah pusat rehabilitasi yang tenteram. Rumah sakit semacam ini, banyak tumbuh juga di Swiss, hingga saat ini.
Namun Solsana tidak berjalan mulus. Pada tahun-tahun pertama ramai, namun pada akhirnya sepi pasien, bahkan kemudian tutup. “Waktu zaman Jepang masuk ke Indonesia, kami mau tak mau harus meninggalkan Indonesia. Dan semua milik kami, termasuk tanah, dijual,“ kenang Gladys.
Zaman Jepang mengubah segalanya. Kehidupan Surbek yang semula mewah, menjadi terbalik. Beruntung karena mereka orang Swiss, lantas dianggap netral. Kurt pun tidak ditangkap Jepang atau dikirim ke kerja paksa.
Namun yang dialami keluarga ini, cukup membekas. Tentara Jepang memperkosa Gret dan Gladys di depan mata Kurt. "Sejak saat itu, kami tidak berani lagi tidur di rumah. Kami pindah ke rumah sakit,“ kata Gladys.
Miranda Christa, cucu Kurt dan Surbek, mengatakan, bahwa syukurlah Gladys tidak hamil atas perkosaan itu. “Dan sekarang saya lihat, apa yang menimpahnya, bukan lagi masalah besar,“ katanya. Paling tidak, pengungkapan pemerkosaan itu dalam buku Im Herzen Sind Wir Indonesischer, menandakan bahwa tidak ada beban lagi di pikiran Gladys. “Bahkan keluarga besar kami juga menyambutnya dengan baik,“ kata Miranda.
Meskipun memiliki pengalaman buruk dengan tentara Jepang, Gladys justru menemukan cinta pertamanya dengan tentara Jepang. Mimo namanya. “Namun karena zaman perang, cinta itu tak berlanjut,“ kata Gladys.
Kendati begitu, hubungan keduanya terus terjalin melalui surat. Bahkan beberapa kali saling mengunjungi satu sama lain. Gladys ke Jepang atau Mimo ke Bern. “Sekarang mungkin sudah meninggal, karena surat saya tidak dibalas lagi,“ kata Gladys.
Di tengah kekejaman tentara Jepang, keluarga Gladys akhirnya saat itu pindah ke Perth, Australia. Namun di kota ini, mereka tak lama tinggal. Sekeluarga akhirnya kembali pulang kampung ke Swiss. (bersambung)
Spiez, nama desa itu, memang menjadi salah satu desa tetirah di Berner Oberland, dataran tinggi Bern. Berner Oberland yang meliputi Interlaken, Lauterbrunnen serta Grindewald adalah high light kunjungan wisatawan ke Heidiland. Di tempat eksotik ini selain ada gunung, danau, dan ratusan air terjun juga sapi-sapi gemuk yang merumput di lembah hijau ala Swiss.
Di tempat inilah, Gladys Luginbuehl Surbek melewatkan masa tuanya. Usianya sudah sepuh, 93 tahun, tapi ingatannya masih jernih, terutama jika bicara tentang Indonesia, atau tepatnya Hindia Belanda. Matanya berbinar binar mengenang masa lalunya di Indonesia, antara Medan, Palembang dan Bandung. Ketiga tempat itulah yang menancap di hatinya hingga sekarang. “Kalau saya sedih atau saya sakit, saya tetap bisa bahagia jika mengingat masa kecil di Indonesia,“ katanya ketika ditemui KORAN SINDO di kediamannya, baru-baru ini.
Gladys memang warga Swiss yang menjadi saksi hidup zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Dia lahir dan besar hingga remaja di Sumatera dan Jawa Barat. Total di kota-kota sebelum Indonesia berdiri itu, dia tinggal selama 16 tahun. “Karena orang tua saya menjadi dokter di Indonesia,“ kenangnya. “Dokter yang bekerja untuk Kerajaan Belanda tepatnya,” timpalnya.
Orang tua Gladys itu bernama Kurt dan Gret Surbek, yang menjalankan tugasnya mulai 1919 di Batang Seponggol, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Namun selain di Batang Seponggol, Gladys juga sering ke Medan. Lalu orang tuanya pindah tugas ke Palembang, Bandung, Perth, Australia dan kembali ke Berner Oberland.
Gladys kini begitu sepuh. Dan, tidak semua mampu diingatnya. Namun catatan harian yang ditinggalkan Gret sebanyak 17 bundel, menjadikan kisah dramatis pasangan ini, termasuk Gladys dan Bernhard atau Bernie, kakaknya, terungkap.
Lewat sebuah buku, Im Herzen Waren Wir Indonesier (Di Dalam Hati Kami, Kami Orang Indonesia) dan sepotong film, Gladys Reise (Perjalanan Gladys), kisah dramatis ini kembali hidup. “Saya masih ingat betul, bagaimana kami dibebaskan oleh orang tua untuk bermain dengan anak kampung, sementara anak-anak orang putih lainnya, dilarang bermain dengan mereka,“ aku Gladys.
Kacung, kuli, jongos bahkan monyet menjadi sebutan umum orang Belanda bagi penduduk pribumi di zaman itu. Tapi Gladys sama sekali tidak melihatnya semacam itu. “Kami main kelereng biasanya, tanpa ada sekat sosial, “ katanya.
Keakraban dengan asisten rumah tangga, juga sangat membekas di hatinya. “Mereka sangat manis, sangat baik kepada kami,“ kata Gladys dengan mata berbinar.
Kurt dan Gret hanya memiliki dua anak. Jika Bernie dilahirkan di Swiss, Gladys lahir di sebuah klinik di Palembang. Kelahiran anak pertama pasangan ini, sengaja dilakukan di Swiss, lantaran belum percaya betul terhadap layanan kesehatan di Hindia Belanda zaman itu. Sementara Gladys dilahirkan di sebuah rumah sakit di Palembang.
Masa itu adalah masa kolonialisme Belanda. Semua orang kulit putih adalah warga negara kelas satu, diikuti warga Asia atau Arab. Adapun yang paling bawah adalah warga pribumi.
Lantaran orangtuanya dokter, kehidupan keluarga Surbek cukup istimewa, bahkan tergolong mewah. Tiap tahun, Kurt bisa berganti mobil. “Lebih baik ganti mobil baru ketimbang istri baru,“ tulis Gret dalam catatan hariannya.
Hobbi mewah Kurt lainnya adalah berburu binatang. Tidak hanya siamang, Kala itu Kurt juga berhasil merobohkan gajah dengan senapannya.
Pada akhirnya, Kurt dan Gret, tentu saja Gladys dan Bernie juga, pindah ke Bandung, Jawa Barat. Hampir sama dengan di Sumatera Utara, kehidupan keluarga ini juga masih mewah. Kurt bahkan mendirikan rumah sakit swasta di Lembang, Jawa Barat. Namanya Solsana, sebuah pusat rehabilitasi yang tenteram. Rumah sakit semacam ini, banyak tumbuh juga di Swiss, hingga saat ini.
Namun Solsana tidak berjalan mulus. Pada tahun-tahun pertama ramai, namun pada akhirnya sepi pasien, bahkan kemudian tutup. “Waktu zaman Jepang masuk ke Indonesia, kami mau tak mau harus meninggalkan Indonesia. Dan semua milik kami, termasuk tanah, dijual,“ kenang Gladys.
Zaman Jepang mengubah segalanya. Kehidupan Surbek yang semula mewah, menjadi terbalik. Beruntung karena mereka orang Swiss, lantas dianggap netral. Kurt pun tidak ditangkap Jepang atau dikirim ke kerja paksa.
Namun yang dialami keluarga ini, cukup membekas. Tentara Jepang memperkosa Gret dan Gladys di depan mata Kurt. "Sejak saat itu, kami tidak berani lagi tidur di rumah. Kami pindah ke rumah sakit,“ kata Gladys.
Miranda Christa, cucu Kurt dan Surbek, mengatakan, bahwa syukurlah Gladys tidak hamil atas perkosaan itu. “Dan sekarang saya lihat, apa yang menimpahnya, bukan lagi masalah besar,“ katanya. Paling tidak, pengungkapan pemerkosaan itu dalam buku Im Herzen Sind Wir Indonesischer, menandakan bahwa tidak ada beban lagi di pikiran Gladys. “Bahkan keluarga besar kami juga menyambutnya dengan baik,“ kata Miranda.
Meskipun memiliki pengalaman buruk dengan tentara Jepang, Gladys justru menemukan cinta pertamanya dengan tentara Jepang. Mimo namanya. “Namun karena zaman perang, cinta itu tak berlanjut,“ kata Gladys.
Kendati begitu, hubungan keduanya terus terjalin melalui surat. Bahkan beberapa kali saling mengunjungi satu sama lain. Gladys ke Jepang atau Mimo ke Bern. “Sekarang mungkin sudah meninggal, karena surat saya tidak dibalas lagi,“ kata Gladys.
Di tengah kekejaman tentara Jepang, keluarga Gladys akhirnya saat itu pindah ke Perth, Australia. Namun di kota ini, mereka tak lama tinggal. Sekeluarga akhirnya kembali pulang kampung ke Swiss. (bersambung)
(nfl)