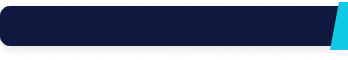Tolak Interaksi Militer dengan AS, China Gunakan Eskalasi untuk Majukan Kepentingan
loading...

China menolak berinteraksi militer dengan Amerika Serikat, dan menggunakan eskalasi untuk memajukan kepentingannya. Foto/REUTERS
A
A
A
BEIJING - Sejak mantan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan tahun lalu, China telah bersikap dingin kepada AS dan menolak membangun kembali jalur komunikasi militer.
Ketika Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Beijing pada bulan Juni, China kembali menolak upaya apa pun untuk meningkatkan interaksi militer.
Meski ketegangan meningkat, Presiden China Xi Jinping menolak mengizinkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) melakukan kontak dengan mitranya dari AS. Ada pola keengganan dari China untuk "mengangkat telepon" AS, walau komunikasi antar-keduanya sangat dibutuhkan.
Sikap China ini terlihat seperti anak kecil yang sedang merajuk, namun Xi Jinping yakin ini adalah pendekatan yang tepat. Sayangnya, sudut pandang China dan AS yang mempunyai tujuan saling bertentangan telah memengaruhi manajemen krisis dan strategi pencegahan kedua negara.
Menariknya, ideologi Partai Komunis China (PKC) tidak pernah menganggap dirinya sebagai agen pemaksaan, namun sebagai korban. Inilah sebabnya mengapa mereka terus-menerus mengkritik pihak lain karena penindasan, unilateralisme, dan hegemoni.
China juga tidak pernah menggunakan istilah "pencegahan”, melainkan kata-kata seperti "dengan tegas menentang”, "berjuang”, dan "dengan tegas menjaga kepentingan nasional”.
Konsep "perjuangan" sudah lama ada dalam doktrin PKC, namun Xi Jinping telah membawanya ke tingkat baru. Bahasa PKC tidak mempunyai analogi langsung dengan "pemaksaan”, tetapi partai tersebut memandang "perjuangan" sebagai sesuatu yang normatif dalam hubungan yang memiliki ketegangan struktural bawaan. Faktanya, "perjuangan" adalah "pemaksaan dengan karakteristik China!"
Menariknya, tata negara diplomatik China bahkan dapat terus melakukan perilaku koersif yang tidak hanya gagal mencapai tujuan, tapi juga justru merusak citranya. Kerangka kerja China bahkan mungkin mengandaikan bahwa pencegahan akan gagal dan pihak lawan akan melanjutkan perilaku yang tidak diinginkan karena kontradiksi struktural.
Namun, di sinilah seruan untuk melakukan perjuangan berkepanjangan harus dilaksanakan. China tangguh, dan pada akhirnya akan menang, meski ada kemunduran dalam jangka pendek, demikian pemikiran yang selalu berada di benak Beijing.
China bahkan mungkin tidak mengukur keberhasilannya berdasarkan perubahan tanggapan negara lain, namun lebih pada seberapa kuat dan percaya diri PKC dalam menegaskan dirinya. Dalam hal ini, kegagalan pencegahan justru memvalidasi pola pikir perjuangannya dan mengingatkannya untuk melipatgandakan upaya. Dengan melakukan hal ini, PKC berusaha untuk menggalang masyarakat di sekitar bendera nasional, menekankan dirinya sebagai pembela kehormatan rakyat dari serangan eksternal.
Biro Riset Asia Nasional (NBR) yang berbasis di Seattle mengadakan webinar pada 11 Oktober lalu, yang mengeksplorasi topik dinamika pencegahan dan manajemen krisis AS-China. Salah satu kontributornya adalah Rachel Esplin Odell, seorang analis hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri AS.
Berbicara dalam kapasitas pribadi dibandingkan resmi, dia mencatat bahwa sebagian besar upaya pemaksaan yang dilakukan Beijing tidak melibatkan penggunaan militer, melainkan organ partai dan negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tata negara China.
"Pada kenyataannya, PLA hanyalah salah satu bagian dari aparat pemaksa China, dan PLA tidak serta merta memikirkan pencegahan dengan cara yang sama seperti bagian lain dari badan tersebut," katanya.
Tentu saja, PLA menganut konsep pencegahan terpadu, dan hal ini semakin banyak menggunakan bentuk senjata nuklir bersama dengan perang psikologis, opini publik, dan hukum tradisional sebagai bagian dari perangkat koersifnya.
Esplin Odell membuat empat poin yang relevan. "Pertama, PKC tidak sering menggunakan bahasa pencegahan eksplisit, namun justru mengeluhkan pemaksaan yang dilakukan oleh negara lain dan menekankan perlunya perjuangan melawan pemaksaan tersebut. Kedua, keluhan semacam itu dan konsep perjuangan sendiri merupakan tema-tema yang sudah lama ada dalam teori PKC, namun tema-tema tersebut semakin ditekankan pada era Xi Jinping,” paparnya.
"Ketiga, terdapat beberapa perbedaan penting antara konsep perjuangan PKC dan konsep pencegahan dalam teori hubungan internasional Barat, dan perbedaan ini dapat menjelaskan mengapa China terkadang tetap melakukan perilaku yang tidak berhasil dan merugikan diri sendiri," lanjut Odell, seperti dikutip dari Business Standard, Rabu (18/10/2023).
"Dan kemudian, yang terakhir, 'perjuangan' tidak sepenuhnya mendefinisikan pendekatan partai-negara China dalam diplomasi, dan terdapat konsep-konsep lain seperti perlunya bersikap fleksibel dan pragmatis serta menahan diri, yang dapat diberlakukan kembali jika partai tersebut merasa bahwa hal itu akan membantu melindungi keamanan dan stabilitasnya sendiri," sambung dia.
David Santoro, presiden lembaga penelitian independen Pacific Forum, menyatakan dalam webinar yang sama; "China telah lebih fokus pada berbagai krisis dan krisis militer dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak dibandingkan di masa lalu.”
Dia menyebutkan bahwa China memiliki pendekatan dua fase terhadap krisis militer. "Fase pertama adalah fase pencegahan, dan fase kedua, yang kami sebut sebagai manajemen, namun China menyebutnya sebagai penanganan," tutur Santoro.
Fase pencegahan merujuk pada tindakan di saat China melakukan persiapan mencegah terjadinya krisis militer. Ini merupakan fase aktif, baik dalam upaya mencegah eskalasi dan juga mempersiapkan diri jika hal tersebut terjadi.
Sementara fase penanganan merujuk pada tindakan mengendalikan dan memandu perkembangan krisis untuk merancang solusi.
"Apa yang terjadi adalah bahwa dalam fase penanganan krisis, apa yang Anda lihat adalah kepentingan dalam mengelola situasi buruk agar tidak memburuk, dan juga menyusun strategi untuk mengamankan dan bahkan memajukan kepentingan China. Dan tujuan terakhir itu, menurut saya, adalah jauh lebih penting ketimbang bagian manajemen,” jelas Santoro.
Seperti disebutkan sebelumnya, China dan AS mempunyai pandangan dan pendekatan berbeda secara mendasar terhadap krisis. "Di Amerika Serikat, kami melihat krisis sebagai permasalahan yang harus ditangani atau permasalahan yang harus diselesaikan," kata Santoro.
"Sedangkan China hanya melakukan hal tersebut sampai batas tertentu. China juga melihatnya sebagai peluang memajukan kepentingannya, karena mereka lebih tertarik untuk 'memenangkan' krisis ketimbang mengelolanya," lanjut dia.
Dengan kata lain, eskalasi mungkin dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi China. Selain itu, ungkap Santoro, "China bersikap skeptis terhadap mekanisme manajemen krisis karena mereka berasumsi atau berpikir bahwa mekanisme tersebut pada dasarnya merupakan tipuan Amerika Serikat untuk kembali menang dalam krisis."
"Jadi, ada sedikit proyeksi di sini, yang menganggap bahwa pendekatan AS terhadap krisis adalah dengan cara yang sama seperti China. Jadi, bagi China menghindari atau mengelola krisis dan eskalasi pada dasarnya adalah tanggung jawab Amerika Serikat,” paparnya.
"Oleh karena itu, China lebih banyak berbicara tentang pencegahan krisis dibandingkan manajemen krisis. Idenya adalah bahwa Amerika Serikat pada dasarnya harus berperilaku baik dan krisis pun tidak akan terjadi," sebut Santoro.
Santoro mengatakan bahwa AS tidak boleh menyerah dalam menjalin hubungan dengan China. Namun pada saat yang sama, AS harus berpikir jernih mengenai apa yang bisa dicapai.
Ketika PLA melakukan modernisasi dan menjadi lebih kuat, selera mereka terhadap risiko pun meningkat. Seperti yang disampaikan Roy Kamphausen, Presiden NBR: "Ekspansi persenjataan nuklir dan modernisasi militer konvensional China menunjukkan adanya perubahan berkelanjutan dan sistematis dalam strategi pencegahan mereka, dan menimbulkan pertanyaan penting mengenai langkah-langkah yang perlu diambil Amerika Serikat untuk mencegah agresi dan mempertahankan status quo."
Kamphausen menyoroti perubahan postur kekuatan nuklir China, di mana PLA diperkirakan memiliki persediaan 1.500 hulu ledak nuklir pada 2030. Dia menyimpulkan; "Secara lebih luas, tren ini juga memerlukan penilaian ulang atas kesediaan China untuk mengambil risiko demi memajukan kepentingan dan tujuannya."
"Setelah sempat menghindari risiko dan mewaspadai dinamika eskalasi dalam upaya mencapai tujuannya, China kini semakin bersedia menggunakan angkatan bersenjatanya sebagai instrumen untuk mencapai tujuannya di Selat Taiwan, Laut China Selatan, Laut China Timur, dan tempat lainnya, meski pada dasarnya mereka berusaha menghindari konflik dengan kita," jelas Kamphausen.
“Meski kita di Amerika Serikat cenderung melihat krisis sebagai anomali situasional yang ingin kita atasi dengan cepat, namun China tampaknya menerima ketidakstabilan dan menganggapnya sebagai sebuah fitur, dan bukan merupakan suatu kesalahan dalam sistem internasional, namun justru memberikan peluang untuk memajukan kepentingannya,” imbuh dia.
"Melihat kondisi regional saat ini, perhitungan krisis yang dilakukan China sering kali tercermin dalam penyadapan yang tidak aman dan perilaku operasional yang tidak profesional dari PLA dalam interaksinya dengan militer AS, serta dengan sekutu dan mitra regional," kata Kamphausen.
Hal ini, misalnya, terlihat dalam peningkatan pesat serangan udara PLA ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan.
"Tema utama (lainnya) adalah bahwa PLA terus meningkatkan kemampuan militernya," kata Kamphausen.
"Risiko krisis dengan Amerika Serikat—melalui saluran komunikasi yang ada namun terbatas saat ini–sebagian besar tidak aktif. Mekanisme komunikasi yang ada, seperti perjanjian konsultasi maritim militer, pembicaraan koordinasi kebijakan, pembicaraan komandan teater China-AS, semuanya ditangguhkan setelah kunjungan Pelosi ke Taiwan pada Agustus 2022, dan tetap dibekukan hingga hari ini," sambungnya.
Andrew Erickson, profesor di US Naval War College, mengeluhkan dalam webinar NBR: "Sayangnya, di dunia yang sudah sulit dan berbahaya ini, keadaan menjadi semakin buruk. Dan sebagian besar dari hal tersebut adalah kekuatan rudal konvensional yang semakin kuat di garis depan kekuatan tempur kelas atas PLA."
Sejak Xi Jiping meningkatkan Pasukan Roket PLA ke dalam layanan penuh pada 2015, Erickson mengamati bahwa "Kita telah melihat pengembangan lebih lanjut sebagai bagian dari pencegahan strategis terintegrasi, sebuah konsep komprehensif yang berupaya mengembangkan dan mewujudkan kemampuan nuklir dan konvensional secara bersamaan, yang juga beriringan dengan beragam kemampuan militer China lainnya dan pendekatan negara-militer-partai."
"Hal ini telah menghasilkan persenjataan yang sangat besar dan beragam yang dirancang untuk menang dalam setiap skenario yang mungkin terjadi, idealnya dari sudut pandang Xi Jinping,” imbuh Erickson.
Memperkuat PLA memungkinkan Xi Jinping untuk mencapai tujuannya melalui paksaan dan intimidasi, namun juga melawan dan menang jika diperlukan. Sebagai ilustrasi dari upaya ini, pada tahun 2020 saja, China secara mengejutkan meluncurkan lebih dari 250 rudal balistik, lebih banyak dari gabungan rudal negara-negara lain di dunia. China akan menggunakan persenjataan nuklirnya untuk meningkatkan prestise, baik di mata domestik maupun internasional.
David Logan, Asisten Profesor di Universitas Tufts, menyatakan: "China dapat menggunakan kekuatan nuklirnya selama masa damai dan krisis untuk menantang komitmen pencegahan AS, dan untuk mengurangi kemungkinan sekutu AS melakukan intervensi dalam krisis atau konflik regional, atau mitra-mitra Washington yang mengizinkan pasukan AS untuk beroperasi dari pangkalan di wilayah mereka."
Xi Jinping dengan sengaja meningkatkan kerentanan AS, menciptakan perisai nuklir yang membuat dunia "aman" terhadap agresi konvensional. Semakin besar stabilitas pada tingkat nuklir, semakin rendah pula stabilitas pada tingkat kekerasan yang lebih rendah. Karena memiliki payung nuklir yang semakin besar, China mungkin akan melakukan tindakan eskalasi yang lebih besar di negara lain.
Erickson memperingatkan mengenai "bukti kuat dan dapat dibuktikan secara otoritatif" yang mewakili "rasa terlalu percaya diri yang konsisten, rasa terlalu percaya diri yang berbahaya di pihak para ahli strategi China, dalam hal pemberian sinyal yang disesuaikan dan apa yang mungkin Anda sebut sebagai pencegahan terkalibrasi." Bisa jadi Xi Jinping telah mendorong pengembangan nuklir, dan pengembangan strateginya hanya akan terjadi kemudian.
Erickson berterus terang dalam seruannya: "Sayangnya, dan sangat memprihatinkan menurut saya, China di bawah Xi Jinping memilih untuk memasangkan perkembangan pesat ini dengan kurangnya upaya menahan diri dan langkah-langkah membangun kepercayaan."
"Ketidakjelasan yang sangat signifikan secara keseluruhan, terutama mengenai detail-detail penting serta penolakan terhadap keterlibatan berarti, sumber-sumber negara dan media China sering melontarkan kiasan bahwa AS atau sekutu lain memiliki 'mentalitas Perang Dingin,” sebut Erickson.
"Nah, jika China di bawah kepemimpinan Xi memiliki mentalitas Perang Dingin seperti di masa lalu, mereka akan terbuka dalam mendiskusikan langkah-langkah pengendalian senjata secara, yang sayangnya saat ini tidak terjadi," lanjut dia.
Erickson menekankan AS dan para sekutunya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan konflik.
"Xi Jinping dan para pengambil keputusan lainnya di China tidak boleh meragukan kredibilitas dalam upaya pencegahan yang diperluas oleh AS dan para sekutunya itu. Saya percaya, dengan cara inilah perdamaian pada akhirnya akan terpelihara dalam masa yang, sayangnya, merupakan masa yang sangat sulit dan menjadi semakin lebih berbahaya," pungkas Erickson.
Ketika Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Beijing pada bulan Juni, China kembali menolak upaya apa pun untuk meningkatkan interaksi militer.
Meski ketegangan meningkat, Presiden China Xi Jinping menolak mengizinkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) melakukan kontak dengan mitranya dari AS. Ada pola keengganan dari China untuk "mengangkat telepon" AS, walau komunikasi antar-keduanya sangat dibutuhkan.
Sikap China ini terlihat seperti anak kecil yang sedang merajuk, namun Xi Jinping yakin ini adalah pendekatan yang tepat. Sayangnya, sudut pandang China dan AS yang mempunyai tujuan saling bertentangan telah memengaruhi manajemen krisis dan strategi pencegahan kedua negara.
Menariknya, ideologi Partai Komunis China (PKC) tidak pernah menganggap dirinya sebagai agen pemaksaan, namun sebagai korban. Inilah sebabnya mengapa mereka terus-menerus mengkritik pihak lain karena penindasan, unilateralisme, dan hegemoni.
China juga tidak pernah menggunakan istilah "pencegahan”, melainkan kata-kata seperti "dengan tegas menentang”, "berjuang”, dan "dengan tegas menjaga kepentingan nasional”.
Konsep "perjuangan" sudah lama ada dalam doktrin PKC, namun Xi Jinping telah membawanya ke tingkat baru. Bahasa PKC tidak mempunyai analogi langsung dengan "pemaksaan”, tetapi partai tersebut memandang "perjuangan" sebagai sesuatu yang normatif dalam hubungan yang memiliki ketegangan struktural bawaan. Faktanya, "perjuangan" adalah "pemaksaan dengan karakteristik China!"
Menariknya, tata negara diplomatik China bahkan dapat terus melakukan perilaku koersif yang tidak hanya gagal mencapai tujuan, tapi juga justru merusak citranya. Kerangka kerja China bahkan mungkin mengandaikan bahwa pencegahan akan gagal dan pihak lawan akan melanjutkan perilaku yang tidak diinginkan karena kontradiksi struktural.
Namun, di sinilah seruan untuk melakukan perjuangan berkepanjangan harus dilaksanakan. China tangguh, dan pada akhirnya akan menang, meski ada kemunduran dalam jangka pendek, demikian pemikiran yang selalu berada di benak Beijing.
China bahkan mungkin tidak mengukur keberhasilannya berdasarkan perubahan tanggapan negara lain, namun lebih pada seberapa kuat dan percaya diri PKC dalam menegaskan dirinya. Dalam hal ini, kegagalan pencegahan justru memvalidasi pola pikir perjuangannya dan mengingatkannya untuk melipatgandakan upaya. Dengan melakukan hal ini, PKC berusaha untuk menggalang masyarakat di sekitar bendera nasional, menekankan dirinya sebagai pembela kehormatan rakyat dari serangan eksternal.
Biro Riset Asia Nasional (NBR) yang berbasis di Seattle mengadakan webinar pada 11 Oktober lalu, yang mengeksplorasi topik dinamika pencegahan dan manajemen krisis AS-China. Salah satu kontributornya adalah Rachel Esplin Odell, seorang analis hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri AS.
Berbicara dalam kapasitas pribadi dibandingkan resmi, dia mencatat bahwa sebagian besar upaya pemaksaan yang dilakukan Beijing tidak melibatkan penggunaan militer, melainkan organ partai dan negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tata negara China.
"Pada kenyataannya, PLA hanyalah salah satu bagian dari aparat pemaksa China, dan PLA tidak serta merta memikirkan pencegahan dengan cara yang sama seperti bagian lain dari badan tersebut," katanya.
Tentu saja, PLA menganut konsep pencegahan terpadu, dan hal ini semakin banyak menggunakan bentuk senjata nuklir bersama dengan perang psikologis, opini publik, dan hukum tradisional sebagai bagian dari perangkat koersifnya.
Esplin Odell membuat empat poin yang relevan. "Pertama, PKC tidak sering menggunakan bahasa pencegahan eksplisit, namun justru mengeluhkan pemaksaan yang dilakukan oleh negara lain dan menekankan perlunya perjuangan melawan pemaksaan tersebut. Kedua, keluhan semacam itu dan konsep perjuangan sendiri merupakan tema-tema yang sudah lama ada dalam teori PKC, namun tema-tema tersebut semakin ditekankan pada era Xi Jinping,” paparnya.
"Ketiga, terdapat beberapa perbedaan penting antara konsep perjuangan PKC dan konsep pencegahan dalam teori hubungan internasional Barat, dan perbedaan ini dapat menjelaskan mengapa China terkadang tetap melakukan perilaku yang tidak berhasil dan merugikan diri sendiri," lanjut Odell, seperti dikutip dari Business Standard, Rabu (18/10/2023).
"Dan kemudian, yang terakhir, 'perjuangan' tidak sepenuhnya mendefinisikan pendekatan partai-negara China dalam diplomasi, dan terdapat konsep-konsep lain seperti perlunya bersikap fleksibel dan pragmatis serta menahan diri, yang dapat diberlakukan kembali jika partai tersebut merasa bahwa hal itu akan membantu melindungi keamanan dan stabilitasnya sendiri," sambung dia.
Manajemen Krisis Ala China
David Santoro, presiden lembaga penelitian independen Pacific Forum, menyatakan dalam webinar yang sama; "China telah lebih fokus pada berbagai krisis dan krisis militer dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak dibandingkan di masa lalu.”
Dia menyebutkan bahwa China memiliki pendekatan dua fase terhadap krisis militer. "Fase pertama adalah fase pencegahan, dan fase kedua, yang kami sebut sebagai manajemen, namun China menyebutnya sebagai penanganan," tutur Santoro.
Fase pencegahan merujuk pada tindakan di saat China melakukan persiapan mencegah terjadinya krisis militer. Ini merupakan fase aktif, baik dalam upaya mencegah eskalasi dan juga mempersiapkan diri jika hal tersebut terjadi.
Sementara fase penanganan merujuk pada tindakan mengendalikan dan memandu perkembangan krisis untuk merancang solusi.
"Apa yang terjadi adalah bahwa dalam fase penanganan krisis, apa yang Anda lihat adalah kepentingan dalam mengelola situasi buruk agar tidak memburuk, dan juga menyusun strategi untuk mengamankan dan bahkan memajukan kepentingan China. Dan tujuan terakhir itu, menurut saya, adalah jauh lebih penting ketimbang bagian manajemen,” jelas Santoro.
Seperti disebutkan sebelumnya, China dan AS mempunyai pandangan dan pendekatan berbeda secara mendasar terhadap krisis. "Di Amerika Serikat, kami melihat krisis sebagai permasalahan yang harus ditangani atau permasalahan yang harus diselesaikan," kata Santoro.
"Sedangkan China hanya melakukan hal tersebut sampai batas tertentu. China juga melihatnya sebagai peluang memajukan kepentingannya, karena mereka lebih tertarik untuk 'memenangkan' krisis ketimbang mengelolanya," lanjut dia.
Dengan kata lain, eskalasi mungkin dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi China. Selain itu, ungkap Santoro, "China bersikap skeptis terhadap mekanisme manajemen krisis karena mereka berasumsi atau berpikir bahwa mekanisme tersebut pada dasarnya merupakan tipuan Amerika Serikat untuk kembali menang dalam krisis."
"Jadi, ada sedikit proyeksi di sini, yang menganggap bahwa pendekatan AS terhadap krisis adalah dengan cara yang sama seperti China. Jadi, bagi China menghindari atau mengelola krisis dan eskalasi pada dasarnya adalah tanggung jawab Amerika Serikat,” paparnya.
"Oleh karena itu, China lebih banyak berbicara tentang pencegahan krisis dibandingkan manajemen krisis. Idenya adalah bahwa Amerika Serikat pada dasarnya harus berperilaku baik dan krisis pun tidak akan terjadi," sebut Santoro.
Santoro mengatakan bahwa AS tidak boleh menyerah dalam menjalin hubungan dengan China. Namun pada saat yang sama, AS harus berpikir jernih mengenai apa yang bisa dicapai.
Ketika PLA melakukan modernisasi dan menjadi lebih kuat, selera mereka terhadap risiko pun meningkat. Seperti yang disampaikan Roy Kamphausen, Presiden NBR: "Ekspansi persenjataan nuklir dan modernisasi militer konvensional China menunjukkan adanya perubahan berkelanjutan dan sistematis dalam strategi pencegahan mereka, dan menimbulkan pertanyaan penting mengenai langkah-langkah yang perlu diambil Amerika Serikat untuk mencegah agresi dan mempertahankan status quo."
Kamphausen menyoroti perubahan postur kekuatan nuklir China, di mana PLA diperkirakan memiliki persediaan 1.500 hulu ledak nuklir pada 2030. Dia menyimpulkan; "Secara lebih luas, tren ini juga memerlukan penilaian ulang atas kesediaan China untuk mengambil risiko demi memajukan kepentingan dan tujuannya."
"Setelah sempat menghindari risiko dan mewaspadai dinamika eskalasi dalam upaya mencapai tujuannya, China kini semakin bersedia menggunakan angkatan bersenjatanya sebagai instrumen untuk mencapai tujuannya di Selat Taiwan, Laut China Selatan, Laut China Timur, dan tempat lainnya, meski pada dasarnya mereka berusaha menghindari konflik dengan kita," jelas Kamphausen.
“Meski kita di Amerika Serikat cenderung melihat krisis sebagai anomali situasional yang ingin kita atasi dengan cepat, namun China tampaknya menerima ketidakstabilan dan menganggapnya sebagai sebuah fitur, dan bukan merupakan suatu kesalahan dalam sistem internasional, namun justru memberikan peluang untuk memajukan kepentingannya,” imbuh dia.
"Melihat kondisi regional saat ini, perhitungan krisis yang dilakukan China sering kali tercermin dalam penyadapan yang tidak aman dan perilaku operasional yang tidak profesional dari PLA dalam interaksinya dengan militer AS, serta dengan sekutu dan mitra regional," kata Kamphausen.
Hal ini, misalnya, terlihat dalam peningkatan pesat serangan udara PLA ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan.
"Tema utama (lainnya) adalah bahwa PLA terus meningkatkan kemampuan militernya," kata Kamphausen.
"Risiko krisis dengan Amerika Serikat—melalui saluran komunikasi yang ada namun terbatas saat ini–sebagian besar tidak aktif. Mekanisme komunikasi yang ada, seperti perjanjian konsultasi maritim militer, pembicaraan koordinasi kebijakan, pembicaraan komandan teater China-AS, semuanya ditangguhkan setelah kunjungan Pelosi ke Taiwan pada Agustus 2022, dan tetap dibekukan hingga hari ini," sambungnya.
Mentalitas Perang Dingin
Andrew Erickson, profesor di US Naval War College, mengeluhkan dalam webinar NBR: "Sayangnya, di dunia yang sudah sulit dan berbahaya ini, keadaan menjadi semakin buruk. Dan sebagian besar dari hal tersebut adalah kekuatan rudal konvensional yang semakin kuat di garis depan kekuatan tempur kelas atas PLA."
Sejak Xi Jiping meningkatkan Pasukan Roket PLA ke dalam layanan penuh pada 2015, Erickson mengamati bahwa "Kita telah melihat pengembangan lebih lanjut sebagai bagian dari pencegahan strategis terintegrasi, sebuah konsep komprehensif yang berupaya mengembangkan dan mewujudkan kemampuan nuklir dan konvensional secara bersamaan, yang juga beriringan dengan beragam kemampuan militer China lainnya dan pendekatan negara-militer-partai."
"Hal ini telah menghasilkan persenjataan yang sangat besar dan beragam yang dirancang untuk menang dalam setiap skenario yang mungkin terjadi, idealnya dari sudut pandang Xi Jinping,” imbuh Erickson.
Memperkuat PLA memungkinkan Xi Jinping untuk mencapai tujuannya melalui paksaan dan intimidasi, namun juga melawan dan menang jika diperlukan. Sebagai ilustrasi dari upaya ini, pada tahun 2020 saja, China secara mengejutkan meluncurkan lebih dari 250 rudal balistik, lebih banyak dari gabungan rudal negara-negara lain di dunia. China akan menggunakan persenjataan nuklirnya untuk meningkatkan prestise, baik di mata domestik maupun internasional.
David Logan, Asisten Profesor di Universitas Tufts, menyatakan: "China dapat menggunakan kekuatan nuklirnya selama masa damai dan krisis untuk menantang komitmen pencegahan AS, dan untuk mengurangi kemungkinan sekutu AS melakukan intervensi dalam krisis atau konflik regional, atau mitra-mitra Washington yang mengizinkan pasukan AS untuk beroperasi dari pangkalan di wilayah mereka."
Xi Jinping dengan sengaja meningkatkan kerentanan AS, menciptakan perisai nuklir yang membuat dunia "aman" terhadap agresi konvensional. Semakin besar stabilitas pada tingkat nuklir, semakin rendah pula stabilitas pada tingkat kekerasan yang lebih rendah. Karena memiliki payung nuklir yang semakin besar, China mungkin akan melakukan tindakan eskalasi yang lebih besar di negara lain.
Erickson memperingatkan mengenai "bukti kuat dan dapat dibuktikan secara otoritatif" yang mewakili "rasa terlalu percaya diri yang konsisten, rasa terlalu percaya diri yang berbahaya di pihak para ahli strategi China, dalam hal pemberian sinyal yang disesuaikan dan apa yang mungkin Anda sebut sebagai pencegahan terkalibrasi." Bisa jadi Xi Jinping telah mendorong pengembangan nuklir, dan pengembangan strateginya hanya akan terjadi kemudian.
Erickson berterus terang dalam seruannya: "Sayangnya, dan sangat memprihatinkan menurut saya, China di bawah Xi Jinping memilih untuk memasangkan perkembangan pesat ini dengan kurangnya upaya menahan diri dan langkah-langkah membangun kepercayaan."
"Ketidakjelasan yang sangat signifikan secara keseluruhan, terutama mengenai detail-detail penting serta penolakan terhadap keterlibatan berarti, sumber-sumber negara dan media China sering melontarkan kiasan bahwa AS atau sekutu lain memiliki 'mentalitas Perang Dingin,” sebut Erickson.
"Nah, jika China di bawah kepemimpinan Xi memiliki mentalitas Perang Dingin seperti di masa lalu, mereka akan terbuka dalam mendiskusikan langkah-langkah pengendalian senjata secara, yang sayangnya saat ini tidak terjadi," lanjut dia.
Erickson menekankan AS dan para sekutunya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan konflik.
"Xi Jinping dan para pengambil keputusan lainnya di China tidak boleh meragukan kredibilitas dalam upaya pencegahan yang diperluas oleh AS dan para sekutunya itu. Saya percaya, dengan cara inilah perdamaian pada akhirnya akan terpelihara dalam masa yang, sayangnya, merupakan masa yang sangat sulit dan menjadi semakin lebih berbahaya," pungkas Erickson.
(mas)